KONSEP AL-KASB AL-ASY’ARIYYAH DAN PRODUKTIVITAS KERJA
DR. H. Hamzah Harun al-Rasyid, MA[2]
ABSTRAK
Kajian ini membahas tentang konsep al-Kasb al-Asy’ariyyah dan peranannya terhadap peningkatan poduktivitas kerja. Permasalahan kajian adalah bagaimanakah eksistensi aliran al-Asy’ariyyah
dalam kehidupan umat Islam, apakah aliran ini telah membelenggu
fikiran dan kebebasan manusia dan menggiring penganutnya kepada sikap
patalisme, determinisme, atau Jabariyyah, bagaimanakah peranan aliran
al-Asy’ariyyah terhadap peningkatan produktivitas kerja. Temuan kajian menyimpulkan bahwa Teologi al-Asy’ariyyah bersifat terbuka, realistis, dan pragmatis, serta bersikap positif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Karena
itu, menilai aliran al-Asy’ariyyah sebagai aliran fatalisme,
determinisme atau Jabariyyah tidaklah tepat, karena teologi ini sangat
menghormati akal sebagai anugerah ilahi, juga menghormati dan menjunjung tinggi naqal sebagai tuntunan ilahi yang senantiasa aktual.
Muqaddimah
Al-Asy’ariyyah, yang dibangun pertama kali oleh Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ismail al-Ash’ary (260-324 H.)([3])
selama sebelas abad dalam khazanah histori Islam, telah mengalami
pasang surut dalam penyebaran dan bervariasi dalam perkembangan
doktrinnya. Aliran ini muncul setelah Abu al-Hasan al-Asy’ary
memaklumkan dirinya keluar dari Muktazilah sebagai aliran yang telah
dianutnya hingga usia 40 tahun. Sejak itu, beliau merumuskan teologi
baru dan mendapatkan banyak pengikut karena dianggap sebagai suatu
bentuk kesinambungan dari faham Sunni ([4]) yang dianut oleh mayoritas umat Islam, tetapi sebelumnya belum pernah diformulasikan secara lengkap dan sistematis.
Fakta sejarah menunjukan, tampilnya al-Asy’ary tepat disaat sedang
menghangatnya pertentangan antara dua kelompok ekstrim yaitu; antara
kaum Muktazilah yang didukung penguasa, dengan kelompok ahli Hadis yang
didukung mayoritas rakyat umum. Upaya al-Asy’ary mendamaikan dua
kelompok ekstrim yang bertentangan tersebut menyebabkan banyak pakar
menilai bahwa aliran al- Asy’ariyyah adalah aliran kalam ‘jalan tengah’
antara faham Muktazilah dan ahli Hadis disatu sisi dan antara kaum
Jabariyyah dan Qadariyyah di sisi yang lain.
Sebagai aliran jalan tengah antara kaum Muktazilah yang rasionalis-metaforis dan kaum ahli Hadis yang
ekstrim tekstualis, maka al-Asy’ariyyah dalam metodologi kalamnya di
samping menggunakan sumber primer berupa teks-teks suci dari al-Qur'an
dan al-Sunnah, separti yang dilakukan oleh ahli Hadis, juga menggunakan
metode rasional berupa mantik atau logik Aristotle, sehingga dia
menggunakan akal dan naqal secara seimbang.
Beberapa abad setelah aliran al-Asy’ariyyah mencapai perkembangan dan penyebarannya yang sempurna, umat Islam di bawah Khilafah Uthmaniyyah,
mulai mundur, sementara dunia Barat mulai bangkit bersama kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sebahagian pemikir Islam
menyimpulkan bahwa salah satu penyebab yang membawa umat Islam kepada
kemunduran itu adalah sikap fatalisme yang menyelubungi mental umat
Islam. Di antara para penulis dan peneliti ada yang menuduh
bahwa teologi al-Asy’ariyyahlah yang harus bertanggung jawab atas
berkembangnya sikap fatalisme tersebut. Mereka menuduh bahwa teologi
al-Asy’ariyyahlah yang membelenggu fikiran dan kebebasan manusia,
sehingga umat Islam, yang mayoritas menjadi penganutnya tergiring kepada
sikap fatalisme atau Jabariyyah.
Permasalahan Kajian
Berdasar uraian diatas, dapat diambil suatu permasalahan kajian yaitu; bagaimanakah eksistensi aliran al-Asy’ariyyah
dalam kehidupan umat Islam, apakah aliran ini telah membelenggu
fikiran dan kebebasan manusia dan menggiring penganutnya kepada sikap
patalisme, determinisme, atau Jabariyyah, bagaimanakah peranan aliran
al-Asy’ariyyah terhadap peningkatan produktivitas kerja?.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan sumber-sumber kepustakaan
yang ada kaitannya dengan masalah utama kajian. Sebagai data primer
yang akan dihinpun dalam Penelitian ini adalah berupa karya-karya Abū
al- Hasan al- Asycarī,
al-Bāqillānī, al-Juwaynī, dan al-gazālī yang berkaitan dengan
metodologi pemikiran dan ajaran teologi mereka. Keempat-empat tokoh ini
dianggap sebagai tokoh-tokoh utama yang telah berhasil mengantar
mazhab al-Asy’ariyyah kearah lebih sempurna sehingga mereka dianggap
sebagai tokoh-tokoh refresentatif yang dapat mewakili tokoh-tokoh
al-Ashacirah lainnya dari segi aspek kemajuan, perkembangan dan kesempurnaan aliran al-Asy’ariyyah. Banyak tokoh lain melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak lepas daripada upaya keempat-empat tokoh tersebut. Dengan kata lain, mereka-mereka inilah merupakan refresentatif yang sesungguhnya dari aliran al-Asy’ariyyah.
Untuk kelengkapan data-data kajian, penulis menggunakan data sekunder,
yakni bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dan diedarkan
dalam bentuk buku, dokumen, majallah, dan lain-lain yan dianggap
relevan, selain bersifat kepustakaan juga bersifat deskriptif yaitu
mengeksplorasi produk-produk pemikiran kalam ulama terdahulu sebagai
bahan perbandingan.
Qadariyyah vs Jabariyyah
Pada
dasarnya, terdapat dua pandangan dalam khazanah pemikiran Islam
menyangkut masalah perbuatan manusia, dalam teologi Islam dikenal dengan
istilah afcal al-cibad. Golongan pertama adalah mereka yang percaya pada karsa bebas dan kemampuan manusia untuk mewujudkan kemauan dan perbuatannya (free will and free act), golongan ini disebut Qadariyyah.[5]
Golongan kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa manusia pada
hakikatnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk mewujudkan keinginan
dan perbuatannya, karena segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh
Allah sebagai pencipta manusia. Golongan yang berfaham predestinasi
ini disebut Jabariyyah.[6]
Qadariyyah,
dalam hal ini Muktazilah, sangat menitik beratkan tanggung jawab
manusia atas setiap perbuatannya. Mereka menolak faham yang berpendapat
bahwa Allah berkuasa mutlak atas setiap perbuatan manusia.([7]) Menurut
Muktazilah, dengan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya, manusia
mampu membedakan (memilih) perbuatan baik dan buruk. ([8]) Dengan
kemampuan dan kebebasan itulah manusia berkuasa menciptakan nasibnya
sendiri. Dengan demikian, setiap perbuatan manusia, baik atau buruk,
beriman atau kufur, ditentukan oleh dirinya sendiri.([9]) Allah tidak dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan manusia. Separti dinyatakan Ghaylan,
bahwa manusia melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan
sendiri, dan melakukan perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri.
([10])
Di sini kelihatan manusia merdeka atas kemauan dan tingkah lakunya,
apakah ia mau berbuat baik atau berbuat buruk; beriman atau kufur
terhadap Allah. Atas perbuatan yang dilakukannya itu, manusia memperoleh
balasan yang sepadan atau setimpal dari Allah. Sesuai dengan sifat
keadilan Allah, maka di samping memberikan perintah kepada manusia untuk
berbuat sesuatu, Allah membekali manusia dengan daya atau kekuatan
untuk berbuat. Allah Yang Maha Adil tidak mungkin mengingkari diri-Nya
sendiri dengan berbuat zalim kepada manusia, ([11]) yaitu,
tidak memberikan daya dan kekuatan bagi manusia guna mewujudkan
perbuatannya yang berkaitan dengan perintah dan larangan-Nya.
Pandangan
Qadariyyah tersebut, selain menggunakan pendekatan rasional, juga
berpijak pada dalil-dalil al-Qurān. Karena itu, tidak tepat kalau
golongan Qadariyyah disebut sebagai kelompok orang-orang yang sudah
tidak percaya lagi kepada wahyu, sebagaimana ia sering dituduhkan oleh
sebahagian golongan dalam Islam. Beberapa ayat yang sering mereka
jadikan sebagai landasan pendapatnya, antara lain adalah firman Allah
s.w.t: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر[12] beraksud: “Kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau, silahkan beriman dan siapa yang mau menyangkal silakan tidak percaya”. Juga firman Allah : “ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم[13] beraksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (umat) kecuali mereka sendiri yang mengubahnya”.
Berbeda dengan Qadariyyah, kaum Jabariyyah berpendapat sebaliknya,
bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atas kehendak dan
perbuatannya. ([14]) Mereka yakin, kekuasaan Allah tiada terbatas. Allah adalah Pencipta segala sesuatu, termasuk manusia dan perbuatannya. [15] Jabariyyah
menyatakan bahwa setiap gerak dan perbuatan apa pun yang terjadi di
alam semesta ini berlangsung atas kudrat dan iradat Ilahi. Jika
dikatakan ada kehendak, gerak, atau perbuatan yang terjadi di luar
kudrat dan iradat Ilahi, separti perbuatan manusia, berarti kekuasaan
Allah terbatas. Dan mustahil Allah bersifat terbatas. Hal itu, menurut
Jabariyyah, berarti mengakui adanya pelaku lain di alam semesta ini
selain Allah swt. ([16])
Jabariyyah dalam mengemukakan fikiran-fikirannya, juga mengambil nas-nas al-Qur’an, antara lain: firman Allah: يخلق ما يشاء bermaksud “Dialah yang menciptakan apa yang Ia kehendaki”.[17] Juga فان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء bermaksud “Sesungguhnya Allah membiarkan sesat siapa yang dikehendaki-Nya dan dipimpin-Nya siapa yang dikehendaki-Nya”.[18] Ayat lain yang dijadikan sandaran adalah: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها[19] bermaksud: “Tidak
ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu, kecuali yang telah
ditentukan di dalam buku sebelum Kami laksanakan terjadinya”.
Konsep al-Kasb
Untuk menengahi kedua faham tersebut Abu Hasan al-Ashcari mengajukan konsep al-kasb, dengan pengertian bahwa yang mewujudkan perbuatan manusia adalah Allah, ([20])
namun manusia diberi daya dan pilihan untuk berbuat atas kehendak
Allah. Manusia dalam perbuatannya banyak bergantung kepada kehendak dan
kekuasaan Allah. Oleh karena itu, manusia, dalam pandangan al-Ashcari, bukan facil, tetapi kasib. Berdasarkan itulah muncul teori al-kasb. Al-Shahrustani memperjelas pengertian al-kasb
dengan menyatakan bahwa lahirnya perbuatan manusia adalah dengan jalan
Allah memperlakukan sunnah-Nya melalui daya yang baru diciptakan
bersama-sama dengan terjadinya perbuatan. Berkaitan dengan itu, lahirlah
konsep al-iktisab. ([21])
Arti al-iktisab, menurut al-Ashcari, ialah bahwa sesuatu terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan atau kasb bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. ([22]) Di dalam al-Lumac, al-Ashcari memberikan penjelasan yang sama. Arti yang sebenarnya dari al-kasb ialah bahwa sesuatu timbul dari al-muktasib (acquirer, yang memperoleh) dengan perantaraan daya yang diciptakan. ([23])
Argumen yang dimajukan oleh al-Ashcari tentang diciptakannya kasb oleh Allah adalah firman Allah yang bermaksud: “Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”.([24]) Berdasarkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. [25] Tidak ada pembuat atau facil bagi kasb kecuali Allah.[26] Dengan perkataan lain, yang menentukan wujudnya kasb atau perbuatan manusia, dalam pandangan al-Ashcari, sebenarnya adalah Allah sendiri.
Dari keterangan diatas dapat difahami bahwa; sejak masa Ashcari, polemik dan kontroversi tentang perbuatan manusia, dalam teologi dikenal dengan istilah afcal al-cibad, hingga kini tetap hangat diperbincangkan. Terutama kaum Muktazilah yang selalu memunculkan ide qadariyyah atau free will yang menjadi anutan mereka. Dalam suasana demikian al-Ashcarī, sebagai tokoh kalam sunni
terpanggil mengemukakan idenya seiring dengan metodologi yang ia
kembangkan untuk menjembatani antara dua kelompok ekstrim, Jabariyyah
dan Qadariyyah[27] dengan menawarkan konsep ‘teologi poros tengah’ (moderat).
Dalil naql yang dijadikan dasar diciptakannya kasb([28]) itu adalah firman Allah s.w.t.:والله خلقكم وما تعملون “Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”.[29] Kata وما تعملون dalam ayat tersebut diartikan oleh al-Ashcarī dengan “apa yang kamu perbuat” dan bukan “apa yang kamu buat”. Hal ini berarti Allah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Jadi, menurut al-Ashcarī, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Allah, dan Dia pulalah yang membuat kasb. ([30]) Dengan kata lain, bahwa Allah yang mewujudkan kasb atas
perbuatan manusia. Dengan demikian, berarti Allah sebenarnya yang
menjadikan (pembuat) perbuatan manusia, sedangkan manusia hanya
merupakan tempat berlakunya perbuatan-perbuatan Allah tersebut.
Al-Ashcari membagi perbuatan atau gerakan manusia terbahagi kepada idtirar (perbuatan tanpa sengaja, di luar kemampuan) dan perbuatan kasb. Masing-masing perbuatan itu mempunyai dua unsur. Bagi idtirar memiliki
unsur penggerak yang mewujudkan gerak, dan unsur badan yang bergerak.
Penggerak adalah Allah, sementara badan yang bergerak adalah manusia,
sebab badan yang bergerak menghendaki tempat yang bersifat jasmani.
Sedangkan Allah mustahil mempunyai tempat jasmani. ([31]) Adapun unsur bagi kasb, mengikut al-Ashcari, ialah pembuat dan yang memperoleh perbuatan sebagaimana yang terjadi pada gerakan idtirar. Oleh itu, pembuat kasb yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan yang memperoleh kasb adalah manusia.([32])
Al-Ashcari berusaha membedakan antara perbuatan idtirar dan kasb. Pada perbuatan pertama terdapat unsur ‘keterpaksaan’ manusia melakukan sesuatu tanpa dapat dihindarinya, walaupun ia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu. Sedangkan dalam perbuatan yang kedua, tidak terdapat unsur ‘paksaan’ di dalamnya. Namun keduanya itu adalah perbuatan Allah. ([33]) Argumen ini, sesuai dengan firman Allah: وما تشاءون الا أن يشاء الله[34] “Kamu tidak menghendaki kecuali bila dikehendaki oleh Allah”. Maksud ayat ini, menurut al-Ashcari,
adalah bahwa manusia tidak dapat menghendaki sesuatu tanpa dikehendaki
oleh Allah. Jika seseorang berkehendak untuk pergi ke Mekkah, maka
kehendaknya ini akan terlaksana jika Allah menghendakinya. Jadi kehendak
manusia satu dengan kehendak Allah, dan kehendak yang ada dalam diri
manusia itu tidak lain adalah kehendak Allah. ([35])
Adapun mengenai daya, menurut al-Ashcari, diciptakan Allah pada diri manusia sewaktu ia melakukan perbuatan dan tertentu untuk satu kali perbuatan saja. ([36])
Jika demikian, berarti orang yang dalam dirinya tidak memperoleh daya
ciptaan Allah tidak dapat melakukan perbuatan apa pun, dan daya
tersebut tentu selain dari diri manusia. ([37])
Penjelasan ini membawa kepada kesimpulan, bahwa daya untuk mewujudkan
perbuatan sebenarnya bukanlah daya manusia melainkan daya Allah
Sendiri. ([38])
Penjelasan al-Ashcari tentang teori kasb tersebut
sangat jelas, tidak rumit dan tidak membingungkan sebagaimana yang
sering diungkapkan oleh pelbagai pihak yang mengeritiknya([39]) disebabkan karena mereka tidak memahami konsep yang sesungguhnya dari teori al-kasb al-Ashcari. Akibat dari ketidakfaham inilah, banyak orang berkesimpulan bahwa teori kasb al-Ashcari tersebut tergolong dalam faham Jabariyyah. [40])
Yang jelas dalam konsep kasb itu al-Ashcari ingin menyatakan bahwa di dalam perbuatan itu terdapat dua fācil, yaitu
Allah dan manusia. Walaupun manusia itu tidak mempunyai pengaruh yang
efektif, namun dapat difahami bahwa ia tidak mutlak pasif tetapi
justeru aktif walau dalam kadar minimum. Jadi, teori kasb al-Ashcari itu belum dapat dikategorikan sebagai jabari, tetapi tidak pula sebagai qadari. Lagi
pula, suatu penilaian hendaknya jangan terfokus atau terbatas pada isi
dari teori tersebut, melainkan harus pula dilihat bagaimana latar
belakang dan tujuan teori itu diketengahkan.
Al-Ashcari
sebenarnya tidak menginginkan umat terjatuh dalam lingkaran Jabariyyah
dan juga Qadariyyah. Oleh sebab itulah dia mengemukakan sebuah ajaran
yang mengambil posisi jalan tengah, dalam tulisan ini diistilahkan
dengan teologi ‘Poros Tengah’, melalui teori kasb tersebut. Sebagai ajaran pertengahan, tentu yang dimaksudkan oleh al-Ashcari
adalah bahwa manusia, dalam perbuatannya, bebas tapi terikat; terpaksa
tapi masih mempunyai kebebasan. Demikianlah maksud al-Ashcari tersebut. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa di sinilah letak keunikan teologi al-Ashcarī.
Ia memberi peluang kepada generasi berikutnya untuk memberikan
interpretasi dan penjelasan-penjelesan positif, terutama dari
tokoh-tokoh al-Asy’ariyyah.
Al-Bāqillāni dan al-Juwayni,
misalnya, berpendapat bahwa perbuatan terjadi dengan daya manusia,
dengan demikian perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan manusia
itu sendiri. ([41])
Namun, ada perbuatan yang manusia itu terpaksa melakukannya. Misalnya,
manusia manpu berdiri, duduk dan bicara dengan keinginannya sendiri,
tetapi manusia tidak mampu bergerak ketika ia lunpuh dan Sakit. ([42]) Sehubungan dengan itu, al-Bāqillāni menyatakan bahwa manusia hanya mampu berbuat dengan kudrat yang
diciptakan Allah padanya. Ini terlihat bahwa seseorang hanya dapat
berbuat sesuatu pada suatu waktu, tetapi tidak dapat berbuat yang serupa
pada waktu yang lain. ([43])
Selanjutaya, menurut al-Bāqillāni, manusia tidak mampu berbuat sebelum terjadi perbuatan (iktisab). Manusia hanya manpu berbuat ketika terjadi perbuatan (fi hal al-iktisāb), sebab ia tidak diberikan kudrat sebelumnya. ([44]) Berkaitan dengan itu, al-Bāqillāni mengatakan bahwa kudrat yang
ada pada manusia tidak tetap. Karena, apabila ia tetap dengan
sendirinya mestilah ia tetap ada pada waktu yang sama atau pada waktu
yang berlainan, hal ini adalah mustahil. ([45])Karena
itu, kemampuan manusia hanya ada bersamaan dengan perbuatan. Apabila
manusia telah mempunyai kemampuan sebelum terjadi perbuatan, maka pada
waktu terjadi perbuatan itu ia tidak lagi memerlukan bantuan Allah. Maka
yang demikian itu, menurut al-Bāqillāni, mustahil. ([46]) Jadi, dapat dikatakan bahwa Allahlah
yang menciptakan daya pada manusia dan kebebasan manusia terletak pada
penggunaan daya tersebut. Allah s.w.t. memberikan kudrat tidak untuk
dua perbuatan yang bertentangan atau yang sama, atau yang berbeda.
Dengan kata lain, Allah memberikan satu kudrat untuk satu perbuatan. ([47]) Pandangan separti ini, menurut al-Bāqillāni,
tidak menunjukkan seseorang terpaksa dalam perbuatannya. Orang yang
terpaksa berbuat adalah orang yang dibebani sesuatu yang tidak
disukainya. Sementara orang yang dikatakan mampu berbuat adalah orang
yang berbuat dengan kemauannya sendiri. Orang yang terpaksa berbuat dan
yang mampu berbuat berbeda dengan orang yang tidak mampu berbuat sama
sekali. Maka dalam hal ini, orang yang tidak berbuat apa yang
diperintahkan kepadanya adalah orang yang tidak mampu melakukannya. [48]Selain itu, al-Bāqillani mengatakan bahwa Allah memberikan kudrat untuk
berbuat kepada manusia yang sebelumnya tidak ada. Kudrat itu ada
bersamaan dengan terlaksananya perbuatan. Sebagaimana sebuah cincin
bergerak bersamaan dengan kejadian gerakan tangan. Begitu juga seseorang
baru mengetahui rasa sakit bersamaan dengan adanya sakit itu sendiri. ([49]) Argumen ini diperkuat dengan firman Allah : لا يكلف الله نفسا إلا وسعــهــا[50] “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Firman Allah: لا يكلف الله نفســا إلا مــا ءاتاهـــا[51] “Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang
diberikan Allah kepadanya”. Kedua-dua ayat ini, menurut al-Bāqillani, menunjukkan bahwa tidak ada kudrat sebelum perbuatan. ([52]) Dan dalam al-Quran dijelaskan kewajipan bagi orang yang berat menjalankan suatu perbuatan untuk membayar fidyah. ([53]) Hal ini, kata al-Bāqillani jelas menunjukkan tidak adanya kudrat. ([54])
Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa al-Ashcari dan al-Bāqillāni sependapat dalam memandang perbuatan manusia sebagai ciptaan Allah, namun al-Bāqillāni telah menyempurnakan pendapat gurunya, al-Ashcari, dengan mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan di dalam perbuatannya. al-Bāqillāni memandang al-kasb sebagai gerakan orang yang disertai kudrat pada
waktu terjadinya perbuatan, berbeda dengan orang yang lumpuh, yang
tidak dapat bergerak. Ia membedakan antara gerakan tangan orang yang sehat,
sebagai gerakan yang tidak terpaksa, dengan gerakan orang yang
gementar karena sakit, yaitu yang bergerak karena terpaksa. Oleh karena
al-kasb merupakan perbuatan melalui jalan ikhtiar, maka al-kasb bukan perbuatan yang terpaksa.[55] Dengan demikian, konsep al-kasb al-Bāqillāni mengandung
faham kebebasan. Manusia mempunyai peran efektif di dalam
perbuatannya, Allah hanya menciptakan gerak di dalam diri manusia,
sedangkan bentuk dari gerakan itu, yang kemudian disebut perbuatan
seperti duduk, berdiri, berbicara dan sebagainya, adalah perbuatan
manusia. ([56])
Pandangan teologis al-Bāqillāni diatas diteruskan oleh al-Juwayni dengan formulasi bahwa manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam mewujudkan perbuatannya, ([57])
karena ia diberi hak untuk menentukan pilihan, mempergunakan daya yang
telah diciptakan Allah di dalam dirinya dan megamalkan pengetahuan
yang diberikan Allah secara global kepadanya supaya direalisasikan
dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya, al-Juwayni menyatakan bahwa Allah menciptakan daya di dalam diri manusia sebelum terjadinya perbuatan. Daya itu bersifat card (accidentil) dan setiap card tidak kekal. Jadi, karena card sifatnya tidak kekal (al-card la yabqā), tidak dapat digunakan untuk mewujudkan berbagai macam perbuatan.([58]) Untuk terwujudnya suatu perbuatan, mesti ada daya Allah yang menyertainya. ([59])Manusia, menurut al-Juwayni,
bebas mengarahkan daya yang diciptakan Allah itu untuk mewujudkan
perbuatan perbuatannya sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Jadi,
jelas bahwa manusia, menurut al-Juwayni,
mempunyai peranan efektif untuk mengarahkan daya dan mewujudkan
perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya, sedangkan daya untuk mewujudkan
perbuatan itu dengan menggunakan daya Allah. Hal ini terjadi karena
Allah senantiasa memberikan tambahan energi kepada manusia.
Al-Ghazali
juga memberikan keterangan yang sama. Menurutnya, Allahlah yang
menciptakan perbuatan manusia dan kudrat untuk berbuat dalam diri
manusia. ([60])
Perbuatan manusia terjadi dengan kudrat Allah dan bukan dengan kudrat
manusia, sungguhpun yang disebutkan terakhir ini erat hubungannya
dengan perbuatan itu. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa
manusialah yang menciptakan perbuatannya. Untuk itu, kata al-Ghazālī,
sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an, perbuatan manusia
itu disebut al-kasb.[61]
Al-Ghazali memperjelas
adanya kemungkinan dua kudrat dalam satu perbuatan, yaitu kudrat Allah
dan kudrat manusia, karena keterkaitan antara kedua kudrat itu dengan
perbuatan manusia berbeda. Kudrat Allah berkaitan dengan al-khalq (penciptaan), sementara kudrat manusia berkaitan dengan al-kasb. AI-KhaIq berasal dari Allah sedangkan al-kasb berasal daripada manusia. Karena itu, perbuatan manusia disebut al-kasb. ([62])
Peningkatan Produktivitas Kerja
Dari
pemaparan diatas jelaslah bahwa teologi al-Asy’ariyyah adalah teologi
yang yang mementingkan amalan (ikhtiar), sebagaimana yang diisyaratkan
dalam teori al-Kasb. Untuk itu, dalam konteks keimanan, bukan hanya
mengetahui atau membenarkan bahwa Allah itu ada, tetapi juga meletakkan
posisi amal (ikhtiar) amat penting dalam kehidupan. Statement ini
menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh al-Asy’ariyyah dengan teori al-kasb
itu ialah “perolehan” seperangkat alat untuk infrastruktur yang
diberikan kepada manusia untuk diproyeksikan dalam berbagai aspek
kehidupan di dunia. Seperangkat alat itu ialah “ikhtiar dan daya” dalam
perbuatan yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan ‘pahala’
dan ‘dosa’.
Dengan teori al-Kasb maka percaya kepada takdir sama sekali tidak mengandung kesan fatalisme, sebab fatalisme itu mengandung sikap Jabariyyah, menyerah kalah, kepada nasib atau fate yang mengandung tidak ada usaha (inactivity).
Krena itu, percaya kepada takdir yang dikehendaki dalam aliran
al-Ash’ariyyah adalah menyuruh manusia beramal dan berusaha, dan
mustahil ‘takdir’ memiliki makna menentang aktivitas dan amal perbuatan.
Dengan kata lain, adanya ikhtiar dalam perbuatan, di samping tidak
menafikan adanya takdir, ia juga membuat manusia bergairah dan dinamis
dalam melakukan aktivitas.
Dengan demikian, al-kasb berarti manusia tetap memiliki peranan, yaitu berusaha melaksanakan pekerjaannya, walaupun usahanya itu berada dalam ‘batasan’ kekuasaan
mutlak Allah. Dalam perkataan lain, manusia tidak dalam keadaan
terpaksa, tetapi ia juga tidak bebas. Ringkasnya, manusia dalam
perbuatannya tidak terpaksa secara mutlak, namun juga tidak bebas tanpa
batas. Jadi, secara teori al-kasb
mengandung aspek dinamisme. Menilai faktor kedinamisan dan kestatisan,
keaktifan dan kepasifan sesorang, standard yang lazim dipakai adalah
sejauh mana akal mendapat peranan. Dalam konteks ini, teologi
al-Asy’ariyyah, di samping menggunakan argument tekstual, ia juga menggunakan argument rasional. Di dalam Istihsan al-khawd fi cilm al-kalam, al-Ashcari menjelaskan betapa pentingnya penggunaan logika dalam soal caqliyyah sebagaimana pentingnya menggunakan nas dalam masalah syari’at.
Kenyataan diatas semakin memperkuat keyakinan kita bahwa di
dalam faham teologi al-Asy’ariyyah terdapat aspek dinamisme, suatu
aspek yang memotifasi pengikutnya untuk senantiasa berfikir dan
berkarya serta menciptakan penemuan-penemuan baru; mendorong atau
setidak-tidaknya, membiarkan umat untuk melakukan reinterpretasi dan
reaktualisasi terhadap berbagai ajaran agama demi mengantisipasi
perkembangan zaman dan pola kehidupan sosial yang selalu dinamis.
Dengan demikian, teori al-Kasb dalam system teologi al-Asy’ariyyah
dapat merefleksikan suatu sikap dan kreatifitas diri dalam menghadapi
hidup dan kehidupan sehari-sehari, bahkan yang lebih penting dari itu
adalah memberi spirit untuk berbuat dan melaksanakan fungsi kekhalifahan
dalam merespons segala dampak kemajuan tamaddun (peradaban)
dunia saat ini. Oleh itu, bekerja adalah sebahagian daripada ibadah,
dan itulah yang dimaksud sebagai ‘produktivitas kerja’ yang mesti
diperjuangkan oleh umat Islam.
Sebagai inplementasi dari keyakinan diatas, maka menurut ajaran Islam, setiap kali seorang Muslim akan memulai segala aktivitas diperintahkan untuk mengucapkan basmalah, yaitu Bismi Allah al-Rahman al-Rahim. Apapun yang dilakukan, maka mulailah dengan perkataan tersebut. Dengan mengucapkan basmalah,
seseorang bukan hanya sekedar mengharapkan “berkah”, tetapi juga
menghayati maknanya, sehingga dapat melahirkan sikap dan produktifitas
yang positif.
Kata bi yang terletak diawal kalimat basmalah, diterjemahkan ‘dengan’, yang oleh para ulama dikaitkan dengan kata ‘memulai’, sehingga pengucap basmalah
pada hakikatnya berkata: “dengan atau demi Allah saya memulai
pekerjaan ini”. Apabila kita menjadikan pekerjaan kita ‘atas nama
Allah’, maka pekerjaan tersebut pasti tidak akan mengakibatkan kerugian
pihak lain, dan juga tidak akan menimbulkan kerusakan pada harta benda
orang lain. Karena ketika itu, kita telah membentengi diri dan
pekerjaan kita dari godaan nafsu serta ambisi peribadi. Kata bi juga dikaitkan dengan ‘kekuasaan dan pertolongan’, sehingga si pengucap basmalah
menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya terlaksana atas kekuasaan
(kudrat) Allah. Ia memohon bantuan Allah agar pekerjaannya dapat
terselesaikan dengan baik dan sempurna. Dengan permohonan itu, maka di
dalam jiwa si pengucap basmalah tertanam rasa kelemahan di
hadapan Allah s.w.t. Namun, pada masa yang sama, tertanam pula kekuatan,
rasa percaya diri, dan optimisme, karena ia merasa memperoleh bantuan
dan kekuatan dari Allah, yakni sumber dari semua kekuatan. Apabila
suatu pekerjaan dilakukan atas bantuan Allah, maka suda pasti ia
sempurna, indah, baik dan benar karena sifat-sifat Allah “berbekas” pada
pekerjaan tersebut.
Argumen diatas semakin mempertegas bahwa betapa pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam teori al-Kasb al-Asy’ariyyah akan memberi pengaruh positif terhadap pengembangan dan peningkatan produktifitas
kerja. Karena teori ini selalu mengorientasikan penganutnya untuk
senatiasa merasa dekat dengan Allah yang pada akhirnya melahirkan sebuah
kesadaran sebagai manusia yang paling lemah dihadapan kekuasaan mutlak
Allah, dan pada masa yang sama ia merasa paling kuat dan percaya diri,
apabila berhadapan dengan makhluk ciptaan Allah, karena ia menyadari
bahwa ia sedang bersama (معية الله) dengan zat Yang Maha Kuat dan Maha Berkuasa.
Dalam
teologi al-Asy’ariyyah, prinsip separti itu dikenal dengan istilah
“aqidah atau tauhid”. Landasan inilah yang seharusnya mendasari sikap,
gerak, dan pola pikir (ittijah) setiap Muslim. Komitmen seseorang terhadap aqidah atau tauhid ini terimplementasi dalam bentuk perilaku (suluk), moraliti (akhlaq), visi (wijhah al-Nazr), dalam meniti kehidupan nyata. Pemahaman yang kuat terhadap konsep seperti ini akan membentuk sebuah sikap dan jati diri yang kuat dalam memproyeksikan sebuah pranata kehidupan yang dinamis, produktiv, dan cinta kemajuan.
Sesungguhnya, bagian-bagian tertentu dari kerangka konseptual teologis ‘tesis Max Weber’ telah banyak diapresiasi untuk mendorong
umat supaya bekerja keras dalam mengatasi kemunduran mereka dalam
bidang ekonomi. Sakralisasi kerja dengan formulasi “kerja adalah bagian
dari ibadah” dapat dibandingkan dengan “kerja keras adalah panggilan
dan harus terlaksana dalam kehidupan duniawi”. Kesuksesan hidup di
dunia ini sebagai konsekwensi logis daripada kerja keras, dan itu merupakan pertanda bahwa orang itu terpilih dan mendapat keselamatan.[63]
Keterangan
di atas mengantar kita kepada sebuah keyakinan bahwa dalam menata
kehidupan yang cerah dan cemerlang di hari esok, maka yang paling
produktif untuk kita lakukan adalah memperbaiki kualitas usaha ikhtiar
kita (al-kasb) terhadap sesuatu yang lebih bermakna, produktif, dan
prosfektif dalam mengantisifasi kemajuan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
PENUTUP
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep teologi al-Asy’ariyyah sama sekali tidak mengandung kesan fatalisme, sebab fatalisme itu mengandung sikap Jabariyyah, menyerah kalah, kepada nasib atau fate yang mengandung tidak ada usaha (inactivity). Karena itu, percaya kepada takdir yang dikehendaki dalam aliran al-Asy’ariyyah adalah menyuruh manusia beramal dan berusaha. Dengan demikian, konsep al-kasb bermakna manusia tetap memiliki peranan, berusaha melaksanakan pekerjaannya, walaupun usahanya itu berada dalam ‘batasan’ kekuasaan mutlak Allah.
RUJUKAN
al-Ashcari, Abu al-Hasan cAli ibn Ismacil 1955. Kitab al-luma’ fi al-radd cala ahl al-ziyaqh wa al-bidac. Masr: Matbacat al-Munir.
al-Ashcari, Abu al-Hasan cAli ibn Ismacil. 1950. Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin. al-Qahirah: Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah.
al-Ashcari, Abu al-Hasan cAli ibn Ismacil. 1985. al-Ibanah can usul al-diyanah. Bayrut: Dar al-Kitab al-cArabi.
al-Baghdadi, 1928M/1346H, Kitab usul al-din, Bayrut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
al-Baghdadi, Abu Mansur cAbd al-Qadir ibn Tahir al-Tamimi. 1928. Kitab usul al-din. Constatinople: Madrasat al- Misriyyah.
al-Baqillani, al-Qadi Abu Bakr. 1957. Kitab al-tamhil al-awa’il wa talkhis al-dala’il. Bayrut: al-Maktabah al-Sharqiyyah.
al-Baqillani. 1963. al-Insaf fi ma yajib ictiqaduh wa la yajuz al-jahl bih. Tahqiq Muhammad Dhahib al-Kawthari, al-Qahirah: Mu’assasat al-Khanji.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1962. Al-iqtisad fi al-ictiqad. Masr: Maktabat Muhammad Subayh.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1966. Tahafut al-falasifah. al-Qahirah: Dar al-Ma’arif.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1970. “Iljam al-cawam can cilm al-kalam” Masr: Maktabat al-Jundi, Jil. 1.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1937. al-Mustasfa min cilm al-usul. Masr: Maktabat Mustafa Muhammad.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1960. Maqasid al-falasifah. Masr: Dar al-Macarif, Cet. 2
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. t.th. Ihya’ culum al-din. Bayrut: Dar al-Fikr, Jil. 2.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad.. 1907. Kitab al-mawaqif. 8 Juz, al-Qahirah: Maktabat al-Sacadah,
al-Ghurabi., cAli Mustafa. 1958. Tarikh al-firaq al-Islamiyyah wa nash’at cilm al-kalam. al-Qahirah: Maktabat Muhammad cAli Sabih, Cet. 2.
al-Ghurabi., cAli Mustafa. 1958. Tarikh al-firaq al-Islamiyyah wa nash’at cilm al-kalam. al-Qahirah: Maktabat Muhammad cAli Sabih, Cet. 2.
al-Juwayni, Abu al-Macali Abd al-Malik ibn al-Shaykh Abi Muhammad. 1959. al-Irshad cala qawatic al-adillah fi usul al-ictiqad. Misr: Matbacat al-Sacadah.
al-Juwayni, Abu al-Macali Abd al-Malik ibn al-Shaykh Abi Muhammad. 1969. al-Shamil fi usul al-din. Tahqiq Faysal Badir cAwn dan Suhayr Muhammad Mukhtar. Iskandariyyah: Mansha’at al-Macarif.
al-Juwayni, Abu al-Macali cAbd al-Malik ibn al-Shaykh Abi Muhammad. 1979. al-cAqidah al-nizamiyyah. al-Qahirah: Maktabat al-Kulliyyah al-Azhariyyah.
al-Shahrastāni. t.th.al-Milal-wa al-nihal, Bayrut: Dār al-Fikr
Ahmad Amin. 1975. Zuhr al-Islam. Al-Qahirah: Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah, Cet. 4.
Ahmad Amin, 1964, Duha al-Islam, al-Qahirah: al-Nahdah, Jil. 3
cAli Sami al-Nashar. t.th. Nash’ah al-fikr al-falsafi fi al-Islam, Masr: Dar al-Fikr al-cArabi.
D.B. Macdonald, 1903,.Deplopment of Muslim Theologi, Jurisprudence and constitusional Theory, London: George Routledge & Sons Ltd
Fazlur Rahman. 1979. Islam, Chicago and London: University of Chicago Press, Second edition
Ibn cAsakir, Abu al-Qasim cAli ibn al-Hasan ibn Hibatullah al-Dimashqi. 1979. Tabyin kadhb al-muftari fi ma nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Ashcari. Bayrut: Dar al-Kitab al-cArabi.
Ibn Taymiyyah. 1980. Dar’ tacarud al-caql wa al-naql, Juz VI, Riyad: Jamicah al-Imam Muhammad bin Sacud al-Islamiyyah,
Jalal Musa. 1975. Nash’at al-Asy’ariyyah wa al-tatawwuruha, Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
Nurcholish Masid, 1984. Khasanah Intelektual Islam, Jakarta: Bulan Bintang.
Subhi, Ahmad Mahmud. 1969. Fi cilm al-kalam. al-Qahirah: Dar al-Macarif.
[1]
Disampaikan dalam Seminar Internasional kerja sama Fak. Ushuluddin UIN
Aladdin dengan Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM Malaysia di Kampus
II UIN Aladdin Samata, tgl 11 Juni 2009.
[2] Alumni UKM Malaysia dan dosen Tetap Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Aladdin Makassar
[3] Mengenai silsilah al-Asy’ary ini, rujuk Ibn ‘Asakir, Tabyin kadhb al-Muftari, hal. 34.
[4] Faham Sunni dalam Islam disebut juga: Ahli Sunah waljamaah, dengan watak utamanya: neutral dalam politik dan moderat dalam faham keagamaan. Lihat Fazlur Rahman, hal. 87.
[5] Istilah Qadariyyah mengandung dua arti. Pertama, qadariyyah yang berasal dari kata qadara yang berarti berkuasa. Qadariyyah
dalam pengartian pertama ini adalah mereka yang memandang manusia
berkuasa dan bebas dalam perbuatan-perbuatannya. Kedua, qadariyyah yang juga berasal dari kata qadara tetapi dengan arti menentukan. Qadariyyah dalam pengartian ini adalah orang-orang yang berpendapat bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali.
Dalam pembahasan ini, Qadariyyah yang dimaksud adalah dalam pengartian
pertama. Sedangkan Qadariyyah menurut pengartian kedua separti dikenal
dalam sejarah teologi Islam, tidak lazim digunakan, tetapi biasa
disebut Jabariyyah.
[6] Nama itu berasal dari kata jabara yang mengandung arti al-zamahu bificlihi, yakni berkewajiban atau terpaksa dalam pekerjaannya. Faham Jabariyyah, menurut cAbd al-Halim Mahmud, kelihatan pertama kali ditonjolkan dalam teologi Islam oleh al-Jacad ibn Dirham. Tetapi yang menyebarkannya adalah Jahm ibn Safwan. Faham ini berkembang pesat pada kekuasaan Daulah Umayyah (661-750 M).
[7] cAbd al-Jabbar, Sharh al-usul al-khamsah hal. 132, 361, 362.
[8] Ibid, hal. 564; al-Shahrastani, al-Milal wa al-nihal, Jil. 1, hal. 59, 63.
[9] Al-Khayyat, hal. 86-87. 198.
[10] Ahmad Amin, Duha al-Islam, hal. 53-54.
[11] Ibid; lihat juga, cAbd al-Jabbar, hal. 301.
[12] Al-Qur’an, al-Kahf (18):29.
[13] Al-Qur’an, al-Racd (13):11. juga Fussilat 41:41; al-Bara'ah 9:70, 111; dan Yunus 10:30.
[14] al-Ghurabi, Tarikh al-firaq al-Islamiyyah, hal. 2930.
[15] lbrahim Madkur, Fi al-falsafah al-Islamiyyah, hal. 27. al-Shahrustani, al-Milal, hal. 86-88.
[16] Demikianlah
pandangan dasar kaum Jabariyyah, yang dalam perkembangan seterusnya
terpilah-pilah dalam beberapa hal kecil. Tetapi, perbedaan-perbedaan
yang terjadi di kalangan Jabariyyah itu tidak mengubah konsepsi
dasarnya. Sebab, pada prinsipnya, mereka tetap tidak menerima adanya
kemauan dan perbutan bebas manusia.
[17] Al-Qur’an, Rum 30:54.
[18] Al-Qur’an, Fatir 35:8.
[19] Al-Qur’an, al-Hadid 57:22. al-Anbiya' 21:23; al-Anfal 8:17.
[20] al-Ashcari, Maqalat al-Islamiyyin, Jil. 1, hal. 315. Al-Bazdawi, Usul al-din, hal. 100.
[21] al-Shahrastani, al-Milal wa al-nihal, hal. 97.
[22] al-Ashcari, Maqalat al-Islamiyyin, Jil. 2, hal. 221.
[23] al-Ashcari, al-Lumac, hal. 76.
[24] Maksud al-Qurān, al-Saffat 37: 96.
[25] al-Ashcari, al-Lumac, hal. 70.
[26] Ibid hal. 72.
[27] Abū Zahrah, Tarikh al-madhahib al-Islāmiyyah, Jil. 1, hal. 187.
[28] al-Ashcarī, al-Ibānah, hal. 243
[29]Al-Qur’an, al-Sāffāt 37:96.
[30] al-Ashcarī, al-Lumac, hal. 70, 72.
[31] Ibid, hal. 73-74.
[32] Ibid.
[33] Ibid., hal. 75-76.
[34] Al-Qur’an, al-Insan 76:30
[35] al-Ashcari, al-Lumac, hal. 93.
[36] Ibid, hal. 93, 96
[37] Ibid
[38] al-Ashcarī, al-Ibānah, hal. 54.
[39] Ahmad Amin, Zuhr al-IsIām, Jil. 4, hal. 83; JaIāl Musa, Nash'at al-Ashcariyyah, hal. 238.
[40] Ahmad Amin, hal. 83.
[41] al-Bāqillānī, al-Tamhid, hal. 346; al-Juwaynī, al-Aqīdah al-nizamiyyah, hal.
34. Pada masa silam, keyakinan semacam itu memupuk keberanian dan
kesabaran dalam jiwa umat Islam untuk menghadapi segala macam tantangan
dan kesukaran kerana inilah umat Islam di zaman silam bersifat dinamis
dan dapat mewujudkan peradaban yang tinggi. Lihat Harun Nasution, hal. 155.
[42] al-Bāqillānī
mengakui adanya andil manusia di dalam perbuatannya. Kerana itu,
manusia memiliki kebebasan di dalam menentukan perbuatan yang
diinginkannya. al-Bāqillānī, , hal. 323.
[43] Ibid., hal. 324,
[44] Ibid.
[45] Ibid., hal. 324
[46] Ibid.
[47] lbid, hal. 326.
[48] Ibid., hal. 331-332.
[49] Ibid., hal. 328.
[50] Al-Qur’an, al-Baqarah (2):286.
[51] Al-Qur’an, al-Talāq (65):7.
[52] Ibid., hal. 239,
[53] Al-Qur’an, al-Baqarah 2:184
[54] Al-Bāqillānī, hal. 239.
[55] Ibid, hal. 347
[56] al-Shahrustani, hal. 97-98.
[57] al-Juwaynī, al-cAqīdah al-nizāmiyyah, hal. 34.
[58] al-Juwaynī, al-Irshād, hal. 217.
[59]Tuhan
adalah pencipta perbuatan manusia. Ertinya Tuhan benar-benar
mengetahui perbuatan manusia secara terperinci. Manusia tidak dikatakan
sebagai pencipta perbuatannya, kerana, kadang-kadang, manusia tidak
mengetahui dan tidak menyedari adanya perbuatan yang sedang
diperbuatnya. Misalnya, ia makan dan minum sewaktu sedang mabuk atau ia
membalikkan tubuhnya ketika sedang tidur, ia berbicara semasa sedang
'ngigau' sakit dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti itu jelas
bukan manusia sendiri yang menciptakanrrya, tetapi Tuhanlah yang
menciptakannya, sebab Ia mengetahui segala perbuatan yang diperbuat
oleh hamba-Nya. Lihat Ibid, hal 190. Idem, al-cAqīdah al-nizāmiyyah, hal. 33.
[60] al-Ghazālī, al-Iqtisād fī al-ictiqād, hal. 49.
[61] Ibid 314
[62] al-Ghazali, al-Iqtisad fi al-Ictiqad, hal. 49.
[63]
Dalam tesisnya, Max Weber menegaskan adanya hubungan antar Etika
Protestan dengan semangat kapitalisme. Semangat Kapitalisme yang
berdasarkan pada cinta ketekunan, berhemat cermat, punya perhitungan,
rasional, dan sanggup menahan diri, menemukan pasangannya dengan
kerangka pemikiran teologi Calvinisme, terutama Puritanisme, iaitu bahwa
keselamatan diberikan Tuhan kepada orang terpilih sesuai dengan takdir
yang telah ditentukan. Karenanya manusia selalu merasa dalam
ketidakpastian, apakah terpilih sehingga memperoleh keselamatan atau
tidak. Dan kewajibannya adalah menganggap dirinya terpilih dan memerangi
keraguannya tentang anggapan tersebut, sebab keraguannya merupakan
pertanda dia tidak terpilih dalam takdir. Untuk menghilangkan
keraguannya itu dia harus bekerja keras, dan keberhasilan dari kerja
keras ini dianggap sebagai pembenaran bahwa dia memang terpilih. Jadi
kerja keras merupakan pangilan dan suatu tugas suci. Kerangka pemikiran
teologi ini melahirkan etos kerja para penganut Protestan yang berhasil
mengembangkan kapitalisme dari dunia Barat. Lihat Taufik Abdullah, Ethos kerja dan perkembangan ekonomi, Jakarta, LP3ES, 1979, hal. 4-10.
KONSEP AL-KASB AL-ASY’ARIYYAH
DAN PERANANNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA[1]
DR. H. Hamzah Harun al-Rasyid, MA[2]
ABSTRAK
Kajian ini membahas tentang konsep al-Kasb al-Asy’ariyyah dan peranannya terhadap peningkatan poduktivitas kerja. Permasalahan kajian adalah bagaimanakah eksistensi aliran al-Asy’ariyyah
dalam kehidupan umat Islam, apakah aliran ini telah membelenggu
fikiran dan kebebasan manusia dan menggiring penganutnya kepada sikap
patalisme, determinisme, atau Jabariyyah, bagaimanakah peranan aliran
al-Asy’ariyyah terhadap peningkatan produktivitas kerja. Temuan kajian menyimpulkan bahwa Teologi al-Asy’ariyyah bersifat terbuka, realistis, dan pragmatis, serta bersikap positif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Karena
itu, menilai aliran al-Asy’ariyyah sebagai aliran fatalisme,
determinisme atau Jabariyyah tidaklah tepat, karena teologi ini sangat
menghormati akal sebagai anugerah ilahi, juga menghormati dan menjunjung tinggi naqal sebagai tuntunan ilahi yang senantiasa aktual.
Muqaddimah
Al-Asy’ariyyah, yang dibangun pertama kali oleh Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ismail al-Ash’ary (260-324 H.)([3])
selama sebelas abad dalam khazanah histori Islam, telah mengalami
pasang surut dalam penyebaran dan bervariasi dalam perkembangan
doktrinnya. Aliran ini muncul setelah Abu al-Hasan al-Asy’ary
memaklumkan dirinya keluar dari Muktazilah sebagai aliran yang telah
dianutnya hingga usia 40 tahun. Sejak itu, beliau merumuskan teologi
baru dan mendapatkan banyak pengikut karena dianggap sebagai suatu
bentuk kesinambungan dari faham Sunni ([4]) yang dianut oleh mayoritas umat Islam, tetapi sebelumnya belum pernah diformulasikan secara lengkap dan sistematis.
Fakta sejarah menunjukan, tampilnya al-Asy’ary tepat disaat sedang
menghangatnya pertentangan antara dua kelompok ekstrim yaitu; antara
kaum Muktazilah yang didukung penguasa, dengan kelompok ahli Hadis yang
didukung mayoritas rakyat umum. Upaya al-Asy’ary mendamaikan dua
kelompok ekstrim yang bertentangan tersebut menyebabkan banyak pakar
menilai bahwa aliran al- Asy’ariyyah adalah aliran kalam ‘jalan tengah’
antara faham Muktazilah dan ahli Hadis disatu sisi dan antara kaum
Jabariyyah dan Qadariyyah di sisi yang lain.
Sebagai aliran jalan tengah antara kaum Muktazilah yang rasionalis-metaforis dan kaum ahli Hadis yang
ekstrim tekstualis, maka al-Asy’ariyyah dalam metodologi kalamnya di
samping menggunakan sumber primer berupa teks-teks suci dari al-Qur'an
dan al-Sunnah, separti yang dilakukan oleh ahli Hadis, juga menggunakan
metode rasional berupa mantik atau logik Aristotle, sehingga dia
menggunakan akal dan naqal secara seimbang.
Beberapa abad setelah aliran al-Asy’ariyyah mencapai perkembangan dan penyebarannya yang sempurna, umat Islam di bawah Khilafah Uthmaniyyah,
mulai mundur, sementara dunia Barat mulai bangkit bersama kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sebahagian pemikir Islam
menyimpulkan bahwa salah satu penyebab yang membawa umat Islam kepada
kemunduran itu adalah sikap fatalisme yang menyelubungi mental umat
Islam. Di antara para penulis dan peneliti ada yang menuduh
bahwa teologi al-Asy’ariyyahlah yang harus bertanggung jawab atas
berkembangnya sikap fatalisme tersebut. Mereka menuduh bahwa teologi
al-Asy’ariyyahlah yang membelenggu fikiran dan kebebasan manusia,
sehingga umat Islam, yang mayoritas menjadi penganutnya tergiring kepada
sikap fatalisme atau Jabariyyah.
Permasalahan Kajian
Berdasar uraian diatas, dapat diambil suatu permasalahan kajian yaitu; bagaimanakah eksistensi aliran al-Asy’ariyyah
dalam kehidupan umat Islam, apakah aliran ini telah membelenggu
fikiran dan kebebasan manusia dan menggiring penganutnya kepada sikap
patalisme, determinisme, atau Jabariyyah, bagaimanakah peranan aliran
al-Asy’ariyyah terhadap peningkatan produktivitas kerja?.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan sumber-sumber kepustakaan
yang ada kaitannya dengan masalah utama kajian. Sebagai data primer
yang akan dihinpun dalam Penelitian ini adalah berupa karya-karya Abū
al- Hasan al- Asycarī,
al-Bāqillānī, al-Juwaynī, dan al-gazālī yang berkaitan dengan
metodologi pemikiran dan ajaran teologi mereka. Keempat-empat tokoh ini
dianggap sebagai tokoh-tokoh utama yang telah berhasil mengantar
mazhab al-Asy’ariyyah kearah lebih sempurna sehingga mereka dianggap
sebagai tokoh-tokoh refresentatif yang dapat mewakili tokoh-tokoh
al-Ashacirah lainnya dari segi aspek kemajuan, perkembangan dan kesempurnaan aliran al-Asy’ariyyah. Banyak tokoh lain melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak lepas daripada upaya keempat-empat tokoh tersebut. Dengan kata lain, mereka-mereka inilah merupakan refresentatif yang sesungguhnya dari aliran al-Asy’ariyyah.
Untuk kelengkapan data-data kajian, penulis menggunakan data sekunder,
yakni bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dan diedarkan
dalam bentuk buku, dokumen, majallah, dan lain-lain yan dianggap
relevan, selain bersifat kepustakaan juga bersifat deskriptif yaitu
mengeksplorasi produk-produk pemikiran kalam ulama terdahulu sebagai
bahan perbandingan.
Qadariyyah vs Jabariyyah
Pada
dasarnya, terdapat dua pandangan dalam khazanah pemikiran Islam
menyangkut masalah perbuatan manusia, dalam teologi Islam dikenal dengan
istilah afcal al-cibad. Golongan pertama adalah mereka yang percaya pada karsa bebas dan kemampuan manusia untuk mewujudkan kemauan dan perbuatannya (free will and free act), golongan ini disebut Qadariyyah.[5]
Golongan kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa manusia pada
hakikatnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk mewujudkan keinginan
dan perbuatannya, karena segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh
Allah sebagai pencipta manusia. Golongan yang berfaham predestinasi
ini disebut Jabariyyah.[6]
Qadariyyah,
dalam hal ini Muktazilah, sangat menitik beratkan tanggung jawab
manusia atas setiap perbuatannya. Mereka menolak faham yang berpendapat
bahwa Allah berkuasa mutlak atas setiap perbuatan manusia.([7]) Menurut
Muktazilah, dengan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya, manusia
mampu membedakan (memilih) perbuatan baik dan buruk. ([8]) Dengan
kemampuan dan kebebasan itulah manusia berkuasa menciptakan nasibnya
sendiri. Dengan demikian, setiap perbuatan manusia, baik atau buruk,
beriman atau kufur, ditentukan oleh dirinya sendiri.([9]) Allah tidak dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan manusia. Separti dinyatakan Ghaylan,
bahwa manusia melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan
sendiri, dan melakukan perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri.
([10])
Di sini kelihatan manusia merdeka atas kemauan dan tingkah lakunya,
apakah ia mau berbuat baik atau berbuat buruk; beriman atau kufur
terhadap Allah. Atas perbuatan yang dilakukannya itu, manusia memperoleh
balasan yang sepadan atau setimpal dari Allah. Sesuai dengan sifat
keadilan Allah, maka di samping memberikan perintah kepada manusia untuk
berbuat sesuatu, Allah membekali manusia dengan daya atau kekuatan
untuk berbuat. Allah Yang Maha Adil tidak mungkin mengingkari diri-Nya
sendiri dengan berbuat zalim kepada manusia, ([11]) yaitu,
tidak memberikan daya dan kekuatan bagi manusia guna mewujudkan
perbuatannya yang berkaitan dengan perintah dan larangan-Nya.
Pandangan
Qadariyyah tersebut, selain menggunakan pendekatan rasional, juga
berpijak pada dalil-dalil al-Qurān. Karena itu, tidak tepat kalau
golongan Qadariyyah disebut sebagai kelompok orang-orang yang sudah
tidak percaya lagi kepada wahyu, sebagaimana ia sering dituduhkan oleh
sebahagian golongan dalam Islam. Beberapa ayat yang sering mereka
jadikan sebagai landasan pendapatnya, antara lain adalah firman Allah
s.w.t: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر[12] beraksud: “Kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau, silahkan beriman dan siapa yang mau menyangkal silakan tidak percaya”. Juga firman Allah : “ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم[13] beraksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (umat) kecuali mereka sendiri yang mengubahnya”.
Berbeda dengan Qadariyyah, kaum Jabariyyah berpendapat sebaliknya,
bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atas kehendak dan
perbuatannya. ([14]) Mereka yakin, kekuasaan Allah tiada terbatas. Allah adalah Pencipta segala sesuatu, termasuk manusia dan perbuatannya. [15] Jabariyyah
menyatakan bahwa setiap gerak dan perbuatan apa pun yang terjadi di
alam semesta ini berlangsung atas kudrat dan iradat Ilahi. Jika
dikatakan ada kehendak, gerak, atau perbuatan yang terjadi di luar
kudrat dan iradat Ilahi, separti perbuatan manusia, berarti kekuasaan
Allah terbatas. Dan mustahil Allah bersifat terbatas. Hal itu, menurut
Jabariyyah, berarti mengakui adanya pelaku lain di alam semesta ini
selain Allah swt. ([16])
Jabariyyah dalam mengemukakan fikiran-fikirannya, juga mengambil nas-nas al-Qur’an, antara lain: firman Allah: يخلق ما يشاء bermaksud “Dialah yang menciptakan apa yang Ia kehendaki”.[17] Juga فان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء bermaksud “Sesungguhnya Allah membiarkan sesat siapa yang dikehendaki-Nya dan dipimpin-Nya siapa yang dikehendaki-Nya”.[18] Ayat lain yang dijadikan sandaran adalah: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها[19] bermaksud: “Tidak
ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu, kecuali yang telah
ditentukan di dalam buku sebelum Kami laksanakan terjadinya”.
Konsep al-Kasb
Untuk menengahi kedua faham tersebut Abu Hasan al-Ashcari mengajukan konsep al-kasb, dengan pengertian bahwa yang mewujudkan perbuatan manusia adalah Allah, ([20])
namun manusia diberi daya dan pilihan untuk berbuat atas kehendak
Allah. Manusia dalam perbuatannya banyak bergantung kepada kehendak dan
kekuasaan Allah. Oleh karena itu, manusia, dalam pandangan al-Ashcari, bukan facil, tetapi kasib. Berdasarkan itulah muncul teori al-kasb. Al-Shahrustani memperjelas pengertian al-kasb
dengan menyatakan bahwa lahirnya perbuatan manusia adalah dengan jalan
Allah memperlakukan sunnah-Nya melalui daya yang baru diciptakan
bersama-sama dengan terjadinya perbuatan. Berkaitan dengan itu, lahirlah
konsep al-iktisab. ([21])
Arti al-iktisab, menurut al-Ashcari, ialah bahwa sesuatu terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan atau kasb bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. ([22]) Di dalam al-Lumac, al-Ashcari memberikan penjelasan yang sama. Arti yang sebenarnya dari al-kasb ialah bahwa sesuatu timbul dari al-muktasib (acquirer, yang memperoleh) dengan perantaraan daya yang diciptakan. ([23])
Argumen yang dimajukan oleh al-Ashcari tentang diciptakannya kasb oleh Allah adalah firman Allah yang bermaksud: “Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”.([24]) Berdasarkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. [25] Tidak ada pembuat atau facil bagi kasb kecuali Allah.[26] Dengan perkataan lain, yang menentukan wujudnya kasb atau perbuatan manusia, dalam pandangan al-Ashcari, sebenarnya adalah Allah sendiri.
Dari keterangan diatas dapat difahami bahwa; sejak masa Ashcari, polemik dan kontroversi tentang perbuatan manusia, dalam teologi dikenal dengan istilah afcal al-cibad, hingga kini tetap hangat diperbincangkan. Terutama kaum Muktazilah yang selalu memunculkan ide qadariyyah atau free will yang menjadi anutan mereka. Dalam suasana demikian al-Ashcarī, sebagai tokoh kalam sunni
terpanggil mengemukakan idenya seiring dengan metodologi yang ia
kembangkan untuk menjembatani antara dua kelompok ekstrim, Jabariyyah
dan Qadariyyah[27] dengan menawarkan konsep ‘teologi poros tengah’ (moderat).
Dalil naql yang dijadikan dasar diciptakannya kasb([28]) itu adalah firman Allah s.w.t.:والله خلقكم وما تعملون “Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”.[29] Kata وما تعملون dalam ayat tersebut diartikan oleh al-Ashcarī dengan “apa yang kamu perbuat” dan bukan “apa yang kamu buat”. Hal ini berarti Allah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Jadi, menurut al-Ashcarī, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Allah, dan Dia pulalah yang membuat kasb. ([30]) Dengan kata lain, bahwa Allah yang mewujudkan kasb atas
perbuatan manusia. Dengan demikian, berarti Allah sebenarnya yang
menjadikan (pembuat) perbuatan manusia, sedangkan manusia hanya
merupakan tempat berlakunya perbuatan-perbuatan Allah tersebut.
Al-Ashcari membagi perbuatan atau gerakan manusia terbahagi kepada idtirar (perbuatan tanpa sengaja, di luar kemampuan) dan perbuatan kasb. Masing-masing perbuatan itu mempunyai dua unsur. Bagi idtirar memiliki
unsur penggerak yang mewujudkan gerak, dan unsur badan yang bergerak.
Penggerak adalah Allah, sementara badan yang bergerak adalah manusia,
sebab badan yang bergerak menghendaki tempat yang bersifat jasmani.
Sedangkan Allah mustahil mempunyai tempat jasmani. ([31]) Adapun unsur bagi kasb, mengikut al-Ashcari, ialah pembuat dan yang memperoleh perbuatan sebagaimana yang terjadi pada gerakan idtirar. Oleh itu, pembuat kasb yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan yang memperoleh kasb adalah manusia.([32])
Al-Ashcari berusaha membedakan antara perbuatan idtirar dan kasb. Pada perbuatan pertama terdapat unsur ‘keterpaksaan’ manusia melakukan sesuatu tanpa dapat dihindarinya, walaupun ia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu. Sedangkan dalam perbuatan yang kedua, tidak terdapat unsur ‘paksaan’ di dalamnya. Namun keduanya itu adalah perbuatan Allah. ([33]) Argumen ini, sesuai dengan firman Allah: وما تشاءون الا أن يشاء الله[34] “Kamu tidak menghendaki kecuali bila dikehendaki oleh Allah”. Maksud ayat ini, menurut al-Ashcari,
adalah bahwa manusia tidak dapat menghendaki sesuatu tanpa dikehendaki
oleh Allah. Jika seseorang berkehendak untuk pergi ke Mekkah, maka
kehendaknya ini akan terlaksana jika Allah menghendakinya. Jadi kehendak
manusia satu dengan kehendak Allah, dan kehendak yang ada dalam diri
manusia itu tidak lain adalah kehendak Allah. ([35])
Adapun mengenai daya, menurut al-Ashcari, diciptakan Allah pada diri manusia sewaktu ia melakukan perbuatan dan tertentu untuk satu kali perbuatan saja. ([36])
Jika demikian, berarti orang yang dalam dirinya tidak memperoleh daya
ciptaan Allah tidak dapat melakukan perbuatan apa pun, dan daya
tersebut tentu selain dari diri manusia. ([37])
Penjelasan ini membawa kepada kesimpulan, bahwa daya untuk mewujudkan
perbuatan sebenarnya bukanlah daya manusia melainkan daya Allah
Sendiri. ([38])
Penjelasan al-Ashcari tentang teori kasb tersebut
sangat jelas, tidak rumit dan tidak membingungkan sebagaimana yang
sering diungkapkan oleh pelbagai pihak yang mengeritiknya([39]) disebabkan karena mereka tidak memahami konsep yang sesungguhnya dari teori al-kasb al-Ashcari. Akibat dari ketidakfaham inilah, banyak orang berkesimpulan bahwa teori kasb al-Ashcari tersebut tergolong dalam faham Jabariyyah. [40])
Yang jelas dalam konsep kasb itu al-Ashcari ingin menyatakan bahwa di dalam perbuatan itu terdapat dua fācil, yaitu
Allah dan manusia. Walaupun manusia itu tidak mempunyai pengaruh yang
efektif, namun dapat difahami bahwa ia tidak mutlak pasif tetapi
justeru aktif walau dalam kadar minimum. Jadi, teori kasb al-Ashcari itu belum dapat dikategorikan sebagai jabari, tetapi tidak pula sebagai qadari. Lagi
pula, suatu penilaian hendaknya jangan terfokus atau terbatas pada isi
dari teori tersebut, melainkan harus pula dilihat bagaimana latar
belakang dan tujuan teori itu diketengahkan.
Al-Ashcari
sebenarnya tidak menginginkan umat terjatuh dalam lingkaran Jabariyyah
dan juga Qadariyyah. Oleh sebab itulah dia mengemukakan sebuah ajaran
yang mengambil posisi jalan tengah, dalam tulisan ini diistilahkan
dengan teologi ‘Poros Tengah’, melalui teori kasb tersebut. Sebagai ajaran pertengahan, tentu yang dimaksudkan oleh al-Ashcari
adalah bahwa manusia, dalam perbuatannya, bebas tapi terikat; terpaksa
tapi masih mempunyai kebebasan. Demikianlah maksud al-Ashcari tersebut. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa di sinilah letak keunikan teologi al-Ashcarī.
Ia memberi peluang kepada generasi berikutnya untuk memberikan
interpretasi dan penjelasan-penjelesan positif, terutama dari
tokoh-tokoh al-Asy’ariyyah.
Al-Bāqillāni dan al-Juwayni,
misalnya, berpendapat bahwa perbuatan terjadi dengan daya manusia,
dengan demikian perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan manusia
itu sendiri. ([41])
Namun, ada perbuatan yang manusia itu terpaksa melakukannya. Misalnya,
manusia manpu berdiri, duduk dan bicara dengan keinginannya sendiri,
tetapi manusia tidak mampu bergerak ketika ia lunpuh dan Sakit. ([42]) Sehubungan dengan itu, al-Bāqillāni menyatakan bahwa manusia hanya mampu berbuat dengan kudrat yang
diciptakan Allah padanya. Ini terlihat bahwa seseorang hanya dapat
berbuat sesuatu pada suatu waktu, tetapi tidak dapat berbuat yang serupa
pada waktu yang lain. ([43])
Selanjutaya, menurut al-Bāqillāni, manusia tidak mampu berbuat sebelum terjadi perbuatan (iktisab). Manusia hanya manpu berbuat ketika terjadi perbuatan (fi hal al-iktisāb), sebab ia tidak diberikan kudrat sebelumnya. ([44]) Berkaitan dengan itu, al-Bāqillāni mengatakan bahwa kudrat yang
ada pada manusia tidak tetap. Karena, apabila ia tetap dengan
sendirinya mestilah ia tetap ada pada waktu yang sama atau pada waktu
yang berlainan, hal ini adalah mustahil. ([45])Karena
itu, kemampuan manusia hanya ada bersamaan dengan perbuatan. Apabila
manusia telah mempunyai kemampuan sebelum terjadi perbuatan, maka pada
waktu terjadi perbuatan itu ia tidak lagi memerlukan bantuan Allah. Maka
yang demikian itu, menurut al-Bāqillāni, mustahil. ([46]) Jadi, dapat dikatakan bahwa Allahlah
yang menciptakan daya pada manusia dan kebebasan manusia terletak pada
penggunaan daya tersebut. Allah s.w.t. memberikan kudrat tidak untuk
dua perbuatan yang bertentangan atau yang sama, atau yang berbeda.
Dengan kata lain, Allah memberikan satu kudrat untuk satu perbuatan. ([47]) Pandangan separti ini, menurut al-Bāqillāni,
tidak menunjukkan seseorang terpaksa dalam perbuatannya. Orang yang
terpaksa berbuat adalah orang yang dibebani sesuatu yang tidak
disukainya. Sementara orang yang dikatakan mampu berbuat adalah orang
yang berbuat dengan kemauannya sendiri. Orang yang terpaksa berbuat dan
yang mampu berbuat berbeda dengan orang yang tidak mampu berbuat sama
sekali. Maka dalam hal ini, orang yang tidak berbuat apa yang
diperintahkan kepadanya adalah orang yang tidak mampu melakukannya. [48]Selain itu, al-Bāqillani mengatakan bahwa Allah memberikan kudrat untuk
berbuat kepada manusia yang sebelumnya tidak ada. Kudrat itu ada
bersamaan dengan terlaksananya perbuatan. Sebagaimana sebuah cincin
bergerak bersamaan dengan kejadian gerakan tangan. Begitu juga seseorang
baru mengetahui rasa sakit bersamaan dengan adanya sakit itu sendiri. ([49]) Argumen ini diperkuat dengan firman Allah : لا يكلف الله نفسا إلا وسعــهــا[50] “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Firman Allah: لا يكلف الله نفســا إلا مــا ءاتاهـــا[51] “Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang
diberikan Allah kepadanya”. Kedua-dua ayat ini, menurut al-Bāqillani, menunjukkan bahwa tidak ada kudrat sebelum perbuatan. ([52]) Dan dalam al-Quran dijelaskan kewajipan bagi orang yang berat menjalankan suatu perbuatan untuk membayar fidyah. ([53]) Hal ini, kata al-Bāqillani jelas menunjukkan tidak adanya kudrat. ([54])
Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa al-Ashcari dan al-Bāqillāni sependapat dalam memandang perbuatan manusia sebagai ciptaan Allah, namun al-Bāqillāni telah menyempurnakan pendapat gurunya, al-Ashcari, dengan mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan di dalam perbuatannya. al-Bāqillāni memandang al-kasb sebagai gerakan orang yang disertai kudrat pada
waktu terjadinya perbuatan, berbeda dengan orang yang lumpuh, yang
tidak dapat bergerak. Ia membedakan antara gerakan tangan orang yang sehat,
sebagai gerakan yang tidak terpaksa, dengan gerakan orang yang
gementar karena sakit, yaitu yang bergerak karena terpaksa. Oleh karena
al-kasb merupakan perbuatan melalui jalan ikhtiar, maka al-kasb bukan perbuatan yang terpaksa.[55] Dengan demikian, konsep al-kasb al-Bāqillāni mengandung
faham kebebasan. Manusia mempunyai peran efektif di dalam
perbuatannya, Allah hanya menciptakan gerak di dalam diri manusia,
sedangkan bentuk dari gerakan itu, yang kemudian disebut perbuatan
seperti duduk, berdiri, berbicara dan sebagainya, adalah perbuatan
manusia. ([56])
Pandangan teologis al-Bāqillāni diatas diteruskan oleh al-Juwayni dengan formulasi bahwa manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam mewujudkan perbuatannya, ([57])
karena ia diberi hak untuk menentukan pilihan, mempergunakan daya yang
telah diciptakan Allah di dalam dirinya dan megamalkan pengetahuan
yang diberikan Allah secara global kepadanya supaya direalisasikan
dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya, al-Juwayni menyatakan bahwa Allah menciptakan daya di dalam diri manusia sebelum terjadinya perbuatan. Daya itu bersifat card (accidentil) dan setiap card tidak kekal. Jadi, karena card sifatnya tidak kekal (al-card la yabqā), tidak dapat digunakan untuk mewujudkan berbagai macam perbuatan.([58]) Untuk terwujudnya suatu perbuatan, mesti ada daya Allah yang menyertainya. ([59])Manusia, menurut al-Juwayni,
bebas mengarahkan daya yang diciptakan Allah itu untuk mewujudkan
perbuatan perbuatannya sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Jadi,
jelas bahwa manusia, menurut al-Juwayni,
mempunyai peranan efektif untuk mengarahkan daya dan mewujudkan
perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya, sedangkan daya untuk mewujudkan
perbuatan itu dengan menggunakan daya Allah. Hal ini terjadi karena
Allah senantiasa memberikan tambahan energi kepada manusia.
Al-Ghazali
juga memberikan keterangan yang sama. Menurutnya, Allahlah yang
menciptakan perbuatan manusia dan kudrat untuk berbuat dalam diri
manusia. ([60])
Perbuatan manusia terjadi dengan kudrat Allah dan bukan dengan kudrat
manusia, sungguhpun yang disebutkan terakhir ini erat hubungannya
dengan perbuatan itu. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa
manusialah yang menciptakan perbuatannya. Untuk itu, kata al-Ghazālī,
sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an, perbuatan manusia
itu disebut al-kasb.[61]
Al-Ghazali memperjelas
adanya kemungkinan dua kudrat dalam satu perbuatan, yaitu kudrat Allah
dan kudrat manusia, karena keterkaitan antara kedua kudrat itu dengan
perbuatan manusia berbeda. Kudrat Allah berkaitan dengan al-khalq (penciptaan), sementara kudrat manusia berkaitan dengan al-kasb. AI-KhaIq berasal dari Allah sedangkan al-kasb berasal daripada manusia. Karena itu, perbuatan manusia disebut al-kasb. ([62])
Peningkatan Produktivitas Kerja
Dari
pemaparan diatas jelaslah bahwa teologi al-Asy’ariyyah adalah teologi
yang yang mementingkan amalan (ikhtiar), sebagaimana yang diisyaratkan
dalam teori al-Kasb. Untuk itu, dalam konteks keimanan, bukan hanya
mengetahui atau membenarkan bahwa Allah itu ada, tetapi juga meletakkan
posisi amal (ikhtiar) amat penting dalam kehidupan. Statement ini
menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh al-Asy’ariyyah dengan teori al-kasb
itu ialah “perolehan” seperangkat alat untuk infrastruktur yang
diberikan kepada manusia untuk diproyeksikan dalam berbagai aspek
kehidupan di dunia. Seperangkat alat itu ialah “ikhtiar dan daya” dalam
perbuatan yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan ‘pahala’
dan ‘dosa’.
Dengan teori al-Kasb maka percaya kepada takdir sama sekali tidak mengandung kesan fatalisme, sebab fatalisme itu mengandung sikap Jabariyyah, menyerah kalah, kepada nasib atau fate yang mengandung tidak ada usaha (inactivity).
Krena itu, percaya kepada takdir yang dikehendaki dalam aliran
al-Ash’ariyyah adalah menyuruh manusia beramal dan berusaha, dan
mustahil ‘takdir’ memiliki makna menentang aktivitas dan amal perbuatan.
Dengan kata lain, adanya ikhtiar dalam perbuatan, di samping tidak
menafikan adanya takdir, ia juga membuat manusia bergairah dan dinamis
dalam melakukan aktivitas.
Dengan demikian, al-kasb berarti manusia tetap memiliki peranan, yaitu berusaha melaksanakan pekerjaannya, walaupun usahanya itu berada dalam ‘batasan’ kekuasaan
mutlak Allah. Dalam perkataan lain, manusia tidak dalam keadaan
terpaksa, tetapi ia juga tidak bebas. Ringkasnya, manusia dalam
perbuatannya tidak terpaksa secara mutlak, namun juga tidak bebas tanpa
batas. Jadi, secara teori al-kasb
mengandung aspek dinamisme. Menilai faktor kedinamisan dan kestatisan,
keaktifan dan kepasifan sesorang, standard yang lazim dipakai adalah
sejauh mana akal mendapat peranan. Dalam konteks ini, teologi
al-Asy’ariyyah, di samping menggunakan argument tekstual, ia juga menggunakan argument rasional. Di dalam Istihsan al-khawd fi cilm al-kalam, al-Ashcari menjelaskan betapa pentingnya penggunaan logika dalam soal caqliyyah sebagaimana pentingnya menggunakan nas dalam masalah syari’at.
Kenyataan diatas semakin memperkuat keyakinan kita bahwa di
dalam faham teologi al-Asy’ariyyah terdapat aspek dinamisme, suatu
aspek yang memotifasi pengikutnya untuk senantiasa berfikir dan
berkarya serta menciptakan penemuan-penemuan baru; mendorong atau
setidak-tidaknya, membiarkan umat untuk melakukan reinterpretasi dan
reaktualisasi terhadap berbagai ajaran agama demi mengantisipasi
perkembangan zaman dan pola kehidupan sosial yang selalu dinamis.
Dengan demikian, teori al-Kasb dalam system teologi al-Asy’ariyyah
dapat merefleksikan suatu sikap dan kreatifitas diri dalam menghadapi
hidup dan kehidupan sehari-sehari, bahkan yang lebih penting dari itu
adalah memberi spirit untuk berbuat dan melaksanakan fungsi kekhalifahan
dalam merespons segala dampak kemajuan tamaddun (peradaban)
dunia saat ini. Oleh itu, bekerja adalah sebahagian daripada ibadah,
dan itulah yang dimaksud sebagai ‘produktivitas kerja’ yang mesti
diperjuangkan oleh umat Islam.
Sebagai inplementasi dari keyakinan diatas, maka menurut ajaran Islam, setiap kali seorang Muslim akan memulai segala aktivitas diperintahkan untuk mengucapkan basmalah, yaitu Bismi Allah al-Rahman al-Rahim. Apapun yang dilakukan, maka mulailah dengan perkataan tersebut. Dengan mengucapkan basmalah,
seseorang bukan hanya sekedar mengharapkan “berkah”, tetapi juga
menghayati maknanya, sehingga dapat melahirkan sikap dan produktifitas
yang positif.
Kata bi yang terletak diawal kalimat basmalah, diterjemahkan ‘dengan’, yang oleh para ulama dikaitkan dengan kata ‘memulai’, sehingga pengucap basmalah
pada hakikatnya berkata: “dengan atau demi Allah saya memulai
pekerjaan ini”. Apabila kita menjadikan pekerjaan kita ‘atas nama
Allah’, maka pekerjaan tersebut pasti tidak akan mengakibatkan kerugian
pihak lain, dan juga tidak akan menimbulkan kerusakan pada harta benda
orang lain. Karena ketika itu, kita telah membentengi diri dan
pekerjaan kita dari godaan nafsu serta ambisi peribadi. Kata bi juga dikaitkan dengan ‘kekuasaan dan pertolongan’, sehingga si pengucap basmalah
menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya terlaksana atas kekuasaan
(kudrat) Allah. Ia memohon bantuan Allah agar pekerjaannya dapat
terselesaikan dengan baik dan sempurna. Dengan permohonan itu, maka di
dalam jiwa si pengucap basmalah tertanam rasa kelemahan di
hadapan Allah s.w.t. Namun, pada masa yang sama, tertanam pula kekuatan,
rasa percaya diri, dan optimisme, karena ia merasa memperoleh bantuan
dan kekuatan dari Allah, yakni sumber dari semua kekuatan. Apabila
suatu pekerjaan dilakukan atas bantuan Allah, maka suda pasti ia
sempurna, indah, baik dan benar karena sifat-sifat Allah “berbekas” pada
pekerjaan tersebut.
Argumen diatas semakin mempertegas bahwa betapa pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam teori al-Kasb al-Asy’ariyyah akan memberi pengaruh positif terhadap pengembangan dan peningkatan produktifitas
kerja. Karena teori ini selalu mengorientasikan penganutnya untuk
senatiasa merasa dekat dengan Allah yang pada akhirnya melahirkan sebuah
kesadaran sebagai manusia yang paling lemah dihadapan kekuasaan mutlak
Allah, dan pada masa yang sama ia merasa paling kuat dan percaya diri,
apabila berhadapan dengan makhluk ciptaan Allah, karena ia menyadari
bahwa ia sedang bersama (معية الله) dengan zat Yang Maha Kuat dan Maha Berkuasa.
Dalam
teologi al-Asy’ariyyah, prinsip separti itu dikenal dengan istilah
“aqidah atau tauhid”. Landasan inilah yang seharusnya mendasari sikap,
gerak, dan pola pikir (ittijah) setiap Muslim. Komitmen seseorang terhadap aqidah atau tauhid ini terimplementasi dalam bentuk perilaku (suluk), moraliti (akhlaq), visi (wijhah al-Nazr), dalam meniti kehidupan nyata. Pemahaman yang kuat terhadap konsep seperti ini akan membentuk sebuah sikap dan jati diri yang kuat dalam memproyeksikan sebuah pranata kehidupan yang dinamis, produktiv, dan cinta kemajuan.
Sesungguhnya, bagian-bagian tertentu dari kerangka konseptual teologis ‘tesis Max Weber’ telah banyak diapresiasi untuk mendorong
umat supaya bekerja keras dalam mengatasi kemunduran mereka dalam
bidang ekonomi. Sakralisasi kerja dengan formulasi “kerja adalah bagian
dari ibadah” dapat dibandingkan dengan “kerja keras adalah panggilan
dan harus terlaksana dalam kehidupan duniawi”. Kesuksesan hidup di
dunia ini sebagai konsekwensi logis daripada kerja keras, dan itu merupakan pertanda bahwa orang itu terpilih dan mendapat keselamatan.[63]
Keterangan
di atas mengantar kita kepada sebuah keyakinan bahwa dalam menata
kehidupan yang cerah dan cemerlang di hari esok, maka yang paling
produktif untuk kita lakukan adalah memperbaiki kualitas usaha ikhtiar
kita (al-kasb) terhadap sesuatu yang lebih bermakna, produktif, dan
prosfektif dalam mengantisifasi kemajuan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
PENUTUP
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep teologi al-Asy’ariyyah sama sekali tidak mengandung kesan fatalisme, sebab fatalisme itu mengandung sikap Jabariyyah, menyerah kalah, kepada nasib atau fate yang mengandung tidak ada usaha (inactivity). Karena itu, percaya kepada takdir yang dikehendaki dalam aliran al-Asy’ariyyah adalah menyuruh manusia beramal dan berusaha. Dengan demikian, konsep al-kasb bermakna manusia tetap memiliki peranan, berusaha melaksanakan pekerjaannya, walaupun usahanya itu berada dalam ‘batasan’ kekuasaan mutlak Allah.
RUJUKAN
al-Ashcari, Abu al-Hasan cAli ibn Ismacil 1955. Kitab al-luma’ fi al-radd cala ahl al-ziyaqh wa al-bidac. Masr: Matbacat al-Munir.
al-Ashcari, Abu al-Hasan cAli ibn Ismacil. 1950. Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin. al-Qahirah: Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah.
al-Ashcari, Abu al-Hasan cAli ibn Ismacil. 1985. al-Ibanah can usul al-diyanah. Bayrut: Dar al-Kitab al-cArabi.
al-Baghdadi, 1928M/1346H, Kitab usul al-din, Bayrut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
al-Baghdadi, Abu Mansur cAbd al-Qadir ibn Tahir al-Tamimi. 1928. Kitab usul al-din. Constatinople: Madrasat al- Misriyyah.
al-Baqillani, al-Qadi Abu Bakr. 1957. Kitab al-tamhil al-awa’il wa talkhis al-dala’il. Bayrut: al-Maktabah al-Sharqiyyah.
al-Baqillani. 1963. al-Insaf fi ma yajib ictiqaduh wa la yajuz al-jahl bih. Tahqiq Muhammad Dhahib al-Kawthari, al-Qahirah: Mu’assasat al-Khanji.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1962. Al-iqtisad fi al-ictiqad. Masr: Maktabat Muhammad Subayh.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1966. Tahafut al-falasifah. al-Qahirah: Dar al-Ma’arif.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1970. “Iljam al-cawam can cilm al-kalam” Masr: Maktabat al-Jundi, Jil. 1.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1937. al-Mustasfa min cilm al-usul. Masr: Maktabat Mustafa Muhammad.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1960. Maqasid al-falasifah. Masr: Dar al-Macarif, Cet. 2
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. t.th. Ihya’ culum al-din. Bayrut: Dar al-Fikr, Jil. 2.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad.. 1907. Kitab al-mawaqif. 8 Juz, al-Qahirah: Maktabat al-Sacadah,
al-Ghurabi., cAli Mustafa. 1958. Tarikh al-firaq al-Islamiyyah wa nash’at cilm al-kalam. al-Qahirah: Maktabat Muhammad cAli Sabih, Cet. 2.
al-Ghurabi., cAli Mustafa. 1958. Tarikh al-firaq al-Islamiyyah wa nash’at cilm al-kalam. al-Qahirah: Maktabat Muhammad cAli Sabih, Cet. 2.
al-Juwayni, Abu al-Macali Abd al-Malik ibn al-Shaykh Abi Muhammad. 1959. al-Irshad cala qawatic al-adillah fi usul al-ictiqad. Misr: Matbacat al-Sacadah.
al-Juwayni, Abu al-Macali Abd al-Malik ibn al-Shaykh Abi Muhammad. 1969. al-Shamil fi usul al-din. Tahqiq Faysal Badir cAwn dan Suhayr Muhammad Mukhtar. Iskandariyyah: Mansha’at al-Macarif.
al-Juwayni, Abu al-Macali cAbd al-Malik ibn al-Shaykh Abi Muhammad. 1979. al-cAqidah al-nizamiyyah. al-Qahirah: Maktabat al-Kulliyyah al-Azhariyyah.
al-Shahrastāni. t.th.al-Milal-wa al-nihal, Bayrut: Dār al-Fikr
Ahmad Amin. 1975. Zuhr al-Islam. Al-Qahirah: Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah, Cet. 4.
Ahmad Amin, 1964, Duha al-Islam, al-Qahirah: al-Nahdah, Jil. 3
cAli Sami al-Nashar. t.th. Nash’ah al-fikr al-falsafi fi al-Islam, Masr: Dar al-Fikr al-cArabi.
D.B. Macdonald, 1903,.Deplopment of Muslim Theologi, Jurisprudence and constitusional Theory, London: George Routledge & Sons Ltd
Fazlur Rahman. 1979. Islam, Chicago and London: University of Chicago Press, Second edition
Ibn cAsakir, Abu al-Qasim cAli ibn al-Hasan ibn Hibatullah al-Dimashqi. 1979. Tabyin kadhb al-muftari fi ma nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Ashcari. Bayrut: Dar al-Kitab al-cArabi.
Ibn Taymiyyah. 1980. Dar’ tacarud al-caql wa al-naql, Juz VI, Riyad: Jamicah al-Imam Muhammad bin Sacud al-Islamiyyah,
Jalal Musa. 1975. Nash’at al-Asy’ariyyah wa al-tatawwuruha, Bayrut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
Nurcholish Masid, 1984. Khasanah Intelektual Islam, Jakarta: Bulan Bintang.
Subhi, Ahmad Mahmud. 1969. Fi cilm al-kalam. al-Qahirah: Dar al-Macarif.
[1]
Disampaikan dalam Seminar Internasional kerja sama Fak. Ushuluddin UIN
Aladdin dengan Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM Malaysia di Kampus
II UIN Aladdin Samata, tgl 11 Juni 2009.
[2] Alumni UKM Malaysia dan dosen Tetap Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Aladdin Makassar
[3] Mengenai silsilah al-Asy’ary ini, rujuk Ibn ‘Asakir, Tabyin kadhb al-Muftari, hal. 34.
[4] Faham Sunni dalam Islam disebut juga: Ahli Sunah waljamaah, dengan watak utamanya: neutral dalam politik dan moderat dalam faham keagamaan. Lihat Fazlur Rahman, hal. 87.
[5] Istilah Qadariyyah mengandung dua arti. Pertama, qadariyyah yang berasal dari kata qadara yang berarti berkuasa. Qadariyyah
dalam pengartian pertama ini adalah mereka yang memandang manusia
berkuasa dan bebas dalam perbuatan-perbuatannya. Kedua, qadariyyah yang juga berasal dari kata qadara tetapi dengan arti menentukan. Qadariyyah dalam pengartian ini adalah orang-orang yang berpendapat bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali.
Dalam pembahasan ini, Qadariyyah yang dimaksud adalah dalam pengartian
pertama. Sedangkan Qadariyyah menurut pengartian kedua separti dikenal
dalam sejarah teologi Islam, tidak lazim digunakan, tetapi biasa
disebut Jabariyyah.
[6] Nama itu berasal dari kata jabara yang mengandung arti al-zamahu bificlihi, yakni berkewajiban atau terpaksa dalam pekerjaannya. Faham Jabariyyah, menurut cAbd al-Halim Mahmud, kelihatan pertama kali ditonjolkan dalam teologi Islam oleh al-Jacad ibn Dirham. Tetapiapi yang menyebarkannya adalah Jahm ibn Safwan. Faham ini berkembang pesat pada kekuasaan Daulah Umayyah (661-750 M).
[7] cAbd al-Jabbar, Sharh al-usul al-khamsah hal. 132, 361, 362.
[8] Ibid, hal. 564; al-Shahrastani, al-Milal wa al-nihal, Jil. 1, hal. 59, 63.
[9] Al-Khayyat, hal. 86-87. 198.
[10] Ahmad Amin, Duha al-Islam, hal. 53-54.
[11] Ibid; lihat juga, cAbd al-Jabbar, hal. 301.
[12] Al-Qur’an, al-Kahf (18):29.
[13] Al-Qur’an, al-Racd (13):11. juga Fussilat 41:41; al-Bara'ah 9:70, 111; dan Yunus 10:30.
[14] al-Ghurabi, Tarikh al-firaq al-Islamiyyah, hal. 2930.
[15] lbrahim Madkur, Fi al-falsafah al-Islamiyyah, hal. 27. al-Shahrustani, al-Milal, hal. 86-88.
[16] Demikianlah
pandangan dasar kaum Jabariyyah, yang dalam perkembangan seterusnya
terpilah-pilah dalam beberapa hal kecil. Tetapi, perbedaan-perbedaan
yang terjadi di kalangan Jabariyyah itu tidak mengubah konsepsi
dasarnya. Sebab, pada prinsipnya, mereka tetap tidak menerima adanya
kemauan dan perbutan bebas manusia.
[17] Al-Qur’an, Rum 30:54.
[18] Al-Qur’an, Fatir 35:8.
[19] Al-Qur’an, al-Hadid 57:22. al-Anbiya' 21:23; al-Anfal 8:17.
[20] al-Ashcari, Maqalat al-Islamiyyin, Jil. 1, hal. 315. Al-Bazdawi, Usul al-din, hal. 100.
[21] al-Shahrastani, al-Milal wa al-nihal, hal. 97.
[22] al-Ashcari, Maqalat al-Islamiyyin, Jil. 2, hal. 221.
[23] al-Ashcari, al-Lumac, hal. 76.
[24] Maksud al-Qurān, al-Saffat 37: 96.
[25] al-Ashcari, al-Lumac, hal. 70.
[26] Ibid hal. 72.
[27] Abū Zahrah, Tarikh al-madhahib al-Islāmiyyah, Jil. 1, hal. 187.
[28] al-Ashcarī, al-Ibānah, hal. 243
[29]Al-Qur’an, al-Sāffāt 37:96.
[30] al-Ashcarī, al-Lumac, hal. 70, 72.
[31] Ibid, hal. 73-74.
[32] Ibid.
[33] Ibid., hal. 75-76.
[34] Al-Qur’an, al-Insan 76:30
[35] al-Ashcari, al-Lumac, hal. 93.
[36] Ibid, hal. 93, 96
[37] Ibid
[38] al-Ashcarī, al-Ibānah, hal. 54.
[39] Ahmad Amin, Zuhr al-IsIām, Jil. 4, hal. 83; JaIāl Musa, Nash'at al-Ashcariyyah, hal. 238.
[40] Ahmad Amin, hal. 83.
[41] al-Bāqillānī, al-Tamhid, hal. 346; al-Juwaynī, al-Aqīdah al-nizamiyyah, hal.
34. Pada masa silam, keyakinan semacam itu memupuk keberanian dan
kesabaran dalam jiwa umat Islam untuk menghadapi segala macam tantangan
dan kesukaran kerana inilah umat Islam di zaman silam bersifat dinamis
dan dapat mewujudkan peradaban yang tinggi. Lihat Harun Nasution, hal. 155.
[42] al-Bāqillānī
mengakui adanya andil manusia di dalam perbuatannya. Kerana itu,
manusia memiliki kebebasan di dalam menentukan perbuatan yang
diinginkannya. al-Bāqillānī, , hal. 323.
[43] Ibid., hal. 324,
[44] Ibid.
[45] Ibid., hal. 324
[46] Ibid.
[47] lbid, hal. 326.
[48] Ibid., hal. 331-332.
[49] Ibid., hal. 328.
[50] Al-Qur’an, al-Baqarah (2):286.
[51] Al-Qur’an, al-Talāq (65):7.
[52] Ibid., hal. 239,
[53] Al-Qur’an, al-Baqarah 2:184
[54] Al-Bāqillānī, hal. 239.
[55] Ibid, hal. 347
[56] al-Shahrustani, hal. 97-98.
[57] al-Juwaynī, al-cAqīdah al-nizāmiyyah, hal. 34.
[58] al-Juwaynī, al-Irshād, hal. 217.
[59]Tuhan
adalah pencipta perbuatan manusia. Ertinya Tuhan benar-benar
mengetahui perbuatan manusia secara terperinci. Manusia tidak dikatakan
sebagai pencipta perbuatannya, kerana, kadang-kadang, manusia tidak
mengetahui dan tidak menyedari adanya perbuatan yang sedang
diperbuatnya. Misalnya, ia makan dan minum sewaktu sedang mabuk atau ia
membalikkan tubuhnya ketika sedang tidur, ia berbicara semasa sedang
'ngigau' sakit dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti itu jelas
bukan manusia sendiri yang menciptakanrrya, tetapi Tuhanlah yang
menciptakannya, sebab Ia mengetahui segala perbuatan yang diperbuat
oleh hamba-Nya. Lihat Ibid, hal 190. Idem, al-cAqīdah al-nizāmiyyah, hal. 33.
[60] al-Ghazālī, al-Iqtisād fī al-ictiqād, hal. 49.
[61] Ibid 314
[62] al-Ghazali, al-Iqtisad fi al-Ictiqad, hal. 49.
[63]
Dalam tesisnya, Max Weber menegaskan adanya hubungan antar Etika
Protestan dengan semangat kapitalisme. Semangat Kapitalisme yang
berdasarkan pada cinta ketekunan, berhemat cermat, punya perhitungan,
rasional, dan sanggup menahan diri, menemukan pasangannya dengan
kerangka pemikiran teologi Calvinisme, terutama Puritanisme, iaitu bahwa
keselamatan diberikan Tuhan kepada orang terpilih sesuai dengan takdir
yang telah ditentukan. Karenanya manusia selalu merasa dalam
ketidakpastian, apakah terpilih sehingga memperoleh keselamatan atau
tidak. Dan kewajibannya adalah menganggap dirinya terpilih dan memerangi
keraguannya tentang anggapan tersebut, sebab keraguannya merupakan
pertanda dia tidak terpilih dalam takdir. Untuk menghilangkan
keraguannya itu dia harus bekerja keras, dan keberhasilan dari kerja
keras ini dianggap sebagai pembenaran bahwa dia memang terpilih. Jadi
kerja keras merupakan pangilan dan suatu tugas suci. Kerangka pemikiran
teologi ini melahirkan etos kerja para penganut Protestan yang berhasil
mengembangkan kapitalisme dari dunia Barat. Lihat Taufik Abdullah, Ethos kerja dan perkembangan ekonomi, Jakarta, LP3ES, 1979, hal. 4-10.







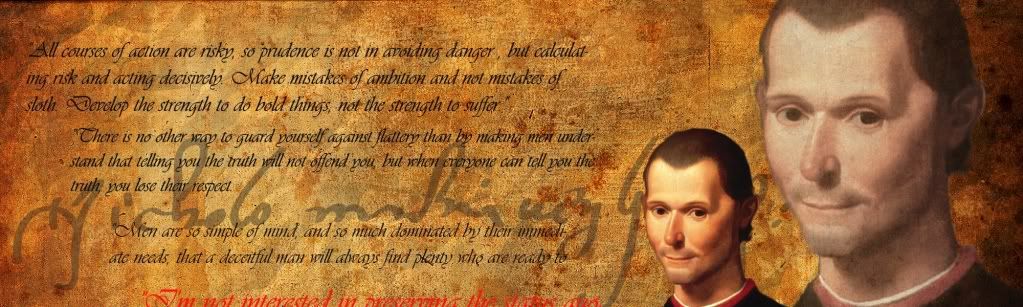

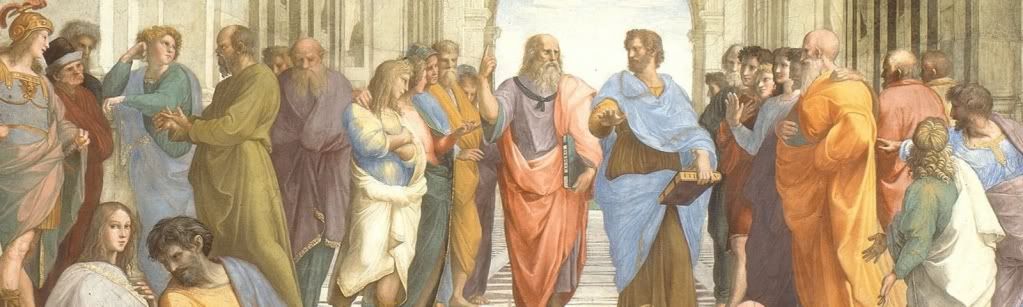
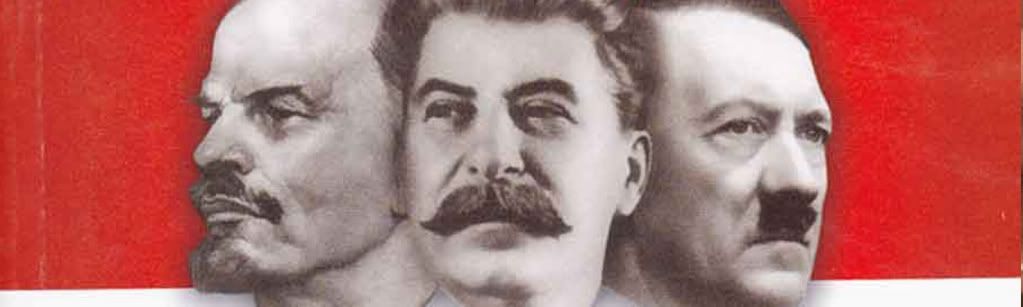



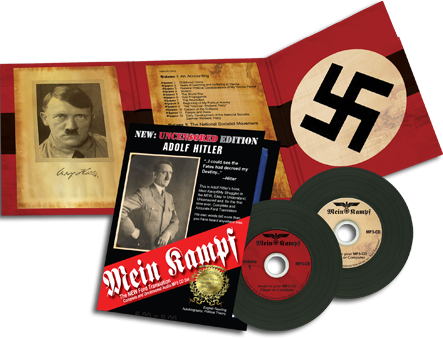
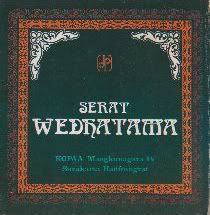


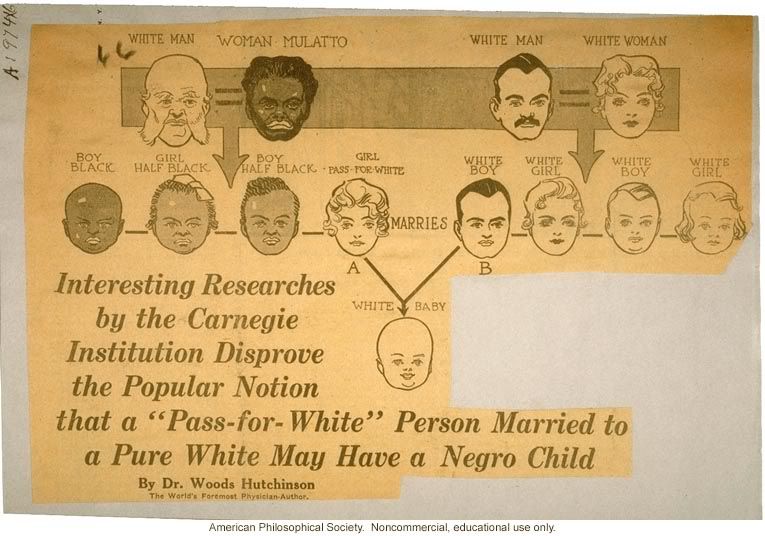
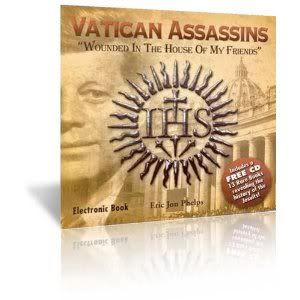









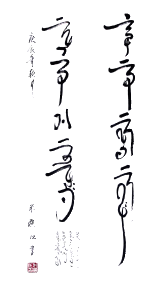
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_special.gif)





