Assalamu ‘Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.
Ustadz
Farid. Mau tanya apakah benar menggulingkan pemerintahan muslim
meskipun zalim itu haram seperti yang terjadi di Mesir sekarang? (Dari 083899369xxx)
Jawaban:
Wa ‘Alaikum salam wa Rahmatullah wa Barakatuh
Bismillah wal hamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala rasulillah wa ‘ala aalihi wa ashhabihi wa man waalah, wa ba’d:
Penguasa
yang zalim lantaran ia banyak penyimpangan dan pelanggaran, fasiq,
korup, otoriter, kesesatan, kufur, menentang hukum Allah Azza wa Jalla. Selalu ada sejak pasca masa-masa khulafa’ur rasyidin hingga
sekarang. Mereka memusuhi ulama dan para da’i Islam, bahkan mengejar,
mengirim mata-mata, memenjarakan dan membunuhnya, namun ada pula yang
justru ‘dibeli’ untuk kepentingan status quonya. Para ulama dan
da’i tersebut menjadi skrup penguat kedudukan penguasa tersebut. Namun,
pada umumnya para ulama dan da’i selalu berseberangan dan menjadi
penentang utama penguasa yang zalim, bahkan manusia secara umum tidak
akan sejalan dengan penguasa seperti itu.
Bagaimana
Islam menyikapi penguasa yang zalim? Paling tidak, ada tiga tahapan
yang bisa dilakukan untuk menyikapinya. Pertama, menasehatinya dengan
hikmah dan pelajaran yang baik agar ia kembali kepada Allah ‘Azza wa Jalla.
Kedua, tidak mentaatinya sampai penguasa itu taat kembali kepada Allah
dan rasulNya. Ketiga, mencopotnya dari jabatannya. Namun yang terakhir
ini diperselisihkan legalitasnya. Bahkan ada yang tega menuduh upaya
mencopot penguasa yang zalim merupakan perilaku khawarij, yang dahulu pernah memberontak kepada Ali radhiallahu ‘anhu.
Sikap-sikap ini akan kita lihat paparannya menurut Al Qur’an, As Sunnah AS Shahihah, dan pandangan ulama ternama masa lalu.
Sikap Pertama. Memberikan Nasihat
Memberikan nasihat kepada penguasa zalim merupakan perintah klasik Allah Jalla wa ‘ Ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ‘alaihimas salam
untuk meluruskan kezaliman Fir’aun. Ini menunjukkan bahwa nasihat dan
ajakan kepada kebaikan merupakan upaya penyembuhan pertama bagi penguasa
zalim, bahkan bagi siapa saja yang menyimpang. Para fuqaha’ sepakat
bahwa hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan shalat secara
sengaja baru bisa ditegakkan bila ia enggan bertaubat setelah
diperintahkan untuknya bertaubat. Memerangi orang kafir pun baru dimulai
ketika da’wah telah ditegakkan, namun mereka membangkang.
Allah Ta’ala berfirman:
“Pergilah engkau (Musa) kepada Fir’aun karena ia telah thagha” (QS. Thaha:24, Qs. An Nazi’at: 17)
“Pergilah engkau berdua (Musa dan Harun) kepada Fir’aun karena ia telah thagha” (QS. Thaha: 43)
Thagha (طغى ) adalah melampaui batas dalam kesombongan dan melakukan penindasan (diktator) (Khalid Abdurrahman Al ‘Ak, Shafwatul Bayan li Ma’anil Qur’anil Karim, hal. 313) juga berarti menyimpang dan sesat (ibid, hal. 314) dan kufur kepada Allah ‘Azza wa Jalla (Ibid, hal. 584)
Berkata Imam Ibnu Katsir -rahimahullah “Maksudnya (Fir’aun) telah melakukan penindasan dan menyombongkan diri.” (Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur’anul Azhim, 4/ 468)
Beliau
juga berkata, “Pergilah engkau (Musa) kepada Fir’aun, penguasa Mesir,
yang telah mengusir dan memerangimu, ajaklah ia untuk ibadah kepada
Allah satu-satunya, tiada sekutu bagiNya, dan hendaknya ia berbuat baik
kepada Bani Israel, jangan menyiksa mereka. Sesungguhnya ia telah
melampaui batas dan membangkang, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia
dan melupakan Rabb yang Maha Tinggi.” (Ibid, 3/146)
Jadi,
ada alasan yang jelas kenapa Fir’aun harus diluruskan karena ia
melampaui batas, sombong, menindas, sesat, kufur dan membangkang kepada
Allah Ta’ala. Inilah ciri khas penguaza zalim, bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja dan kapan saja.
Mengutarakan nasihat dan kalimat yang haq kepada penguasa yang zalim merupakan amal mulia, bahkan disebut sebagai afdhalul jihad (jihad paling utama) (HR. Abu Daud No. 4344. At Tirmidzi No hadits. 2265. Katanya: hadits ini hasan gharib. An Nasa’i No. 4209, Ibnu Majah, No. 4011. Ahmad No. 10716. Dalam riwayat Ahmad tertulis Kalimatul haq (perkataan yang benar). Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini dalam berbagai kitabnya, seperti Shahihul Jami’ No. 1100, 2209, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2174, Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 4344, Shahih wa Dhaif Sunan Ibni Majah No. 4011, dan Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa’i No. 4209)
Bahkan jika ia mati terbunuh karena amar ma’ruf nahi munkar kepada penguasa yang zalim maka ia termasuk penghulu para syuhada, bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. (HR. Al Hakim No. 4884. Ia nyatakan shahih, tetapi Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya. Adz Dzahabi menyepakatinya. Syaikh Al Albany mengatakan hasan, dia memasukkannya dalam kitabnya As Silsilah Ash Shahihah, Juz. No. 374)
Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad Dari radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Agama itu nasihat”, Kami bertanya, “Bagi siapa?”, beliau menjawab, “Bagi Allah, KitabNya, RasulNya, Imam-Imam kaum muslimin dan orang-orang umumnya. “ (HR. Muslim No. 55, At Tirmidzi No. 1990, Ad Darimi No. 2754, Ibnu Hibban No. 4574)
Nasihat yang bagaimana?
Nasihat berasal dari kata nashaha ( ( نصحyang biasa diterjemahkan menasehati. Dalam Lisanul ‘Arab disebutkan Nashaha Syai’ adalah Khalasha (memurnikan/membersihkan). (Ibnu Manzhur, Lisanul ‘Arab, 2/615. Dar Shadir). Jadi, nasihat merupakan upaya pembersihan terhadap kotoran, kesalahan, dan dosa, yang harus dilakukan dengan cara bersih pula.
Tentang da’wah terhadap Fir’aun Allah Ta’ala berfirman:
“Pergilah kalian berdua kepada Fir’aun karena ia telah melampaui batas. Lalu katakanlah untuknya kalimat yang lemah lembut, agar ia ingat dan takut.” (QS. Thaha: 43-44)
Subhanallah! Terhadap fir’aun yang super zalim, Allah Tabaraka wa Ta’ala memerintahkan dua orang utusanNya menda’wahi dengan kata-kata yang lemah lembut (qaulan layyinan),
bukan dengan menghardik dan merendahkannya. Sebab -pada hakikatnya-
dengan kezaliman yang diperbuatnya, posisinya sudah rendah di mata
rakyatnya, dan Allah pun telah merendahkannya. Adapun menda’wahi dengan
kekasaran ucapan dan sikap, justru semakin membuatnya keras dan sombong,
bahkan ia memiliki bala tentara untuk memberangus lawan-lawannya.
Tentunya ini tidak membawa kebaikan bagi da’wah.
Apa tujuannya? ..agar ia ingat dan takut. Ya, agar ia ingat untuk kembali (taubat) dan meninggalkan kesesatannya (Shafwatul Bayan, hal. 314)
bukan agar binasa dan berakhir kekuasaannya. Sebab bila masih ada
kesempatan untuk menjadi orang baik, maka upaya menasihati dengan bijak
adalah lebih utama.
Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal radhiallahu ‘anhu
ucapannya, “Janganlah sekali-kali engkau menentang penguasa, karena
pedangnya selalu terhunus. Tentang apa yang dilakukan orang-orang salaf
(terdahulu) yang berani menentang para penguasa, karena para penguasa
itu enggan kepada ulama. Jika para ulama itu datang, maka mereka akan
menghormati dan tunduk kepada mereka.” (Minhajul Qashidin, hal. 160. Pustaka Al Kautsar, cet. 1. Oktober 1997)
Namun
demikian, betapapun lemah lembutnya menda’wahi penguasa yang zalim,
konsistensi terhadap kebenaran, tidak basa-basi dengan penyimpangan,
adalah sikap yang harus terus dijaga. Sebab biasanya bila sudah memasuki
pintu-pintu penguasa maka keberanian manusia jauh berkurang, terjadi
banyak pemakluman terhadap kedurhakaannya, dan tidak enak hati, itulah
sebabnya Nabi Musa ‘Alaihis salam berdo’a ketika hendak menda’wahi Fir’aun, Rabbisyrahli shadri wa yassirli amri (Tuhanku lapangkan dadaku, mudahkan urusanku)…dst dan ia juga minta kepada Allah Jalla wa ‘Ala berupa bantuan saudaranya, Nabi Harun ‘Alaihis salam, agar kekuatannya bertambah.
Sangat
banyak kisah salafus shalih yang enggan mendekati pintu-pintu istana
khawatir fitnah yang dilahirkannya. Namun tidak sedikit pula salafus
shalih yang berani amar ma’ruf nahi munkar kepada penguasa.
Beberapa kisah nasihat untuk para Penguasa
Said bin Amir pernah berkata kepada khalifah Umar bin al Khathab radhiallahu ‘anhu,
“Sesungguhnya aku akan memberimu nasihat, berupa kata-kata Islam dan
ajaran-ajarannya yang luas maknanya: Takutlah kepada Allah dalam urusan
manusia dan janganlah takut kepada manusia dalam urusan Allah, janganlah
perkataanmu berbeda dengan perbuatanmu, karena sebaik-baik perkataan
adalah yang dibenarkan perbuatan. Cintailah orang-orang muslim yang
dekat dan jauh seperti engkau cintai bagi dirimu dan anggota keluargamu.
Tuntunlah kebodohan kepada kebenaran selagi engkau mengetahuinya.
Janganlah takut celaan orang-orang yang suka mencela.”
Umar bertanya, “Lalu siapa orang yang bisa berbuat seperti itu wahai Abu Said?”
Dia menjawab,”Siapa yang bisa memanggul di atas pundaknya seperti siapa yang memanggul di atas pundakmu.”
Ada
seorang tua renta dari Al Azd yang memasuki tempat tinggal khalifah
Mu’awiyah, lalu dia berkata kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah wahai
Mu’awiyah, dan ketahuilah setiap hari ada yang keluar dari dirimu dan
setiap malam ada yang dating kepadamu, yang tidak memberi tambahan bagi
dunia melainkan semakin jauh dan tidak menambahkan bagi akhirat
melainkan semakin dekat. Di belakangmu ada yang mencari dan engkau tidak
bisa mengelak darinya. Engkau telah mendapatkan ilmu yang tidak bisa
engkau lewatkan. Betapa cepat ilmu yang engkau dapat. Betapa cepat yang
mencarimu akan menghampirimu. Apa yang ada pada dirimu akan segera
berlalu, sementara yang akan kita datangi tetap abadi. Kebaikan pasti
akan dibalas kebaikan dan kejelekan pasti akan dibalas dengan kejelekan
pula.”
Suatu kali khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hazim, “Berilah aku nasihat!”
Abu
Hazim berkata, “Kalau begitu tidurlah telentang, kemudian anggaplah
seakan-akan kematian ada di dekat kepalamu, lalu pikirkanlah sesuatu
yang engkau inginkan saat itu, maka ambillah sekarang juga, sedangkan
apa yang engkau benci pada saat itu, buanglah!” (Ibid, hal. 160-165)
Pada bulan Rajab 1366H Imam Syahid Hasan Al Banna Radhiallahu ‘Anhu
mengirim surat kepada raja Faruq I (Penguasa Mesir dan Sudan), juga
kepada Musthafa an Nuhas Pasya kepala pemerintahan (perdana menteri)
saat itu, juga ditujukan kepada raja-raja, penguasa, pemimpin
negeri-negeri Islam lainnya, dan juga kepada orang-orang yang
berpengaruh dalam urusan agama dan dunia. Inilah mukaddimah surat itu:
Bismillahirrahmanirahim
Segala puji bagi Allah, dan selawat dan salam atas sayyidina Muhammad dan keluarganya, beserta para sahabatnya.
“Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dar sisiMu dan
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.” (QS. Al Kahfi:10)
Kairo, Rajab 1336H
Kepada Yang Terhormat
……….
Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.
Wa ba’du,
Kami persembahkan surat ini kehadapan Tuan yang mulia, dengan keinginan
yang kuat untuk memberi bimbingan kepada umat, yang urusan mereka telah
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah bebankan ke pundak Anda saat
ini. Suatu bimbingan yang semoga dapat mengarahkan umat di atas jalan
yang terbaik. Sebuah jalan yang dibangun oleh sistem hidup terbaik,
bersih dari keguncangan yang tidak pasti, dan telah teruji dalam sejarah
hidup yang panjang.
Kami
tidak mengharap apa pun dari Anda, melainkan bahwa dengan ini kami
telah menunaikan kewajiban dan menyampaikan nasihat untuk Anda. Dan
Pahala dari Allah adalah yang lebih baik dan kekal. (Al Imam Asy Syahid Hasan Al Banna, Majmu’ah Rasail, hal.63-67. Risalah Nahwan nur, Al Maktabah At Taufiqiyah, tanpa tahun)
Demikianlah cuplikan beberapa nasihat para ulama untuk para penguasa, baik penguasa adil atau yang yang zalim.
Saat
ini nasihat untuk penguasa bisa dilakukan melalui surat terbuka di
media massa, surat langsung untuk presiden, bisa melalui parlemen, open hause,
bahkan demonstrasi. Untuk ini (demo) para ulama kontemporer berbeda
pendapat, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Wallahu A’lam
Menasihati Pemimpin Secara Diam-Diam
Menasihati
pemimpin secara diam-diam, memang dianjurkan oleh syariat. Namun, hal
itu tidaklah menunjukkan larangan dengan cara terangan-terangan. Hal ini
hanyalah masalah pilihan uslub (metode). Kedua cara ini pada
kondisi dan jenis kesalahan tertentu, memiliki efektifitas dan
keunggulannya sendiri. Oleh karena itu, tidak dibenarkan saling
meremehkan satu cara dibanding cara yang lain. Tidak seperti prasangkaan
sebagian manusia, bahwa hadits tentang anjuran menasihati pempimpin
secara diam-diam, merupakan petunjuk satu-satunya cara nasihat kepada
pemimpin, dan haram cara lainnya. Prasangkaan ini tidak benar, dan
bertentangan dengan Al Quran serta contoh para nabi, salafush shalih,
dan para ulama rabbani.
Dari ‘Iyadh bin Ghanm Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
مَنْ
أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ
عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ
مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ
“Barangsiapa
yang hendak menasihati pemimpin terhadap suatu urusan, maka janganlah
menampakkannya terang-terangan, tetapi hendaknya dia meraih tangannya
lalu dia menasihatinya berduaan. Jika dia menerima nasihatnya, maka
bagimu akan mendapat ganjaran, jika dia tidak menerima, maka dia telah
menunaikan apa-apa yang layak bagi sultan tersebut.” (HR. Ahmad, No. 15369, Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: shahih lighairih. . Lihat juga Al Musnad Al Jami’, 34/35)
Hadits ini sering dijadikan alasan oleh sebagian kaum
muslimin agar jangan menasihati pemimpin secara terang-terangan bahkan
mereka mengharamkan demonstrasi dengan alasan hadits ini pula.
Anjuran dalam hadits ini adalah agar kita menasihati pemimpin secara face to face atau empat mata. Anjuran yang ada dalam hadits ini, tidaklah sama sekali menunjukkan pembatasan bahwa inilah satu-satunya cara, melainkan hadits ini berbicara tentang salah satu bentuk cara nasihat terhadap pemimpin. Tak ada korelasi apa pun dalam hadits ini yang menunjukkan bahwa terlarangnya menasihati pemimpin secara terbuka. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa para Nabi dan Rasul,
sebagian sahabat, tabi’in, dan para imam kaum muslimin, pernah
menasihati pemimpin secara terang-terangan sebagaimana yang akan kami
paparkan nanti.
Menasihati, Menegur, dan Mengkritik Pemimpin Secara Terang-Terangan
Berikut
ini adalah bukti bahwa cara ini juga pernah dilakukan oleh manusia
mulia. Baik yang melakukannya di istana penguasa atau di tempat selain
istana. Sekaligus paparan di bawah ini sebagai koreksi bagi pihak-pihak
yang melarang menasihati dan menegur kesalahan penguasa secara
terang-terangan.
Zaman Para Nabi ‘Alaihim Shalatu was Salam
Metode ini pun pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah nasihat terbuka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam,
bahkan bukan hanya nasihat, beliau melakukan aksi nyata dengan
menghancurkan berhala-berhala saat itu. Bahkan beliau berdialog dengan
Namrudz dari Babilonia yang disaksikan oleh para pembesar dan
pengawalnya. Sebagaimana yang Allah Ta’ala ceritakan dalam Al Quran:
“Apakah
kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya
(Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan
(kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan
dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan
mematikan".Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari
dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang
kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
zalim.” (QS. Al Baqarah (2): 258)
Tentang
ayat ini, Zaid bin Aslam mengatakan, bahwa raja pertama yang diktator
di muka bumi adalah Namrudz. Manusia keluar rumah serta menjejerkan
makanan di depan Namrudz. Begitu pula Ibrahim pun ikut melakukannya
bersama manusia. Masing-masing mereka dilewati oleh Namrudz dan dia
bertanya; “Siapakah Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Engkaulah!” hingga
giliran Ibrahim, Namrudz bertanya: “Siapakah Tuhanmu?” Ibrahim menjawab:
“Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan.” Namrudz menjawab:
“Aku bisa menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata: “Sesungguhnya
Allah menerbitkan matahari di Timur dan menenggelamkannya di Barat.”
Maka bungkamlah orang kafir itu.” (Imam Abu Ja’far bin Jarir Ath Thabari, Jami’ Al Bayan fi Ta’wilil Quran, 5/433. Muasasah Ar Risalah, Tahqiq: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)
Ayat
ini, dengan gamblang menjelaskan Nabi Ibrahim mengkritik dan mendebat
raja zalim, Namrudz, secara terang-terangan di depan banyak manusia.
Bukti lain bahwa Nabi Ibrahim mengkritik dan mendebat secara
terang-terangan di depan kaumnya adalah isyarat yang Allah Ta’ala
sebutkan dalam ayatNya:
“Dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya.” (QS. Al An’am 96): 83)
Juga yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ‘Alaihimassalam,
mereka berdua menasehati Fir’aun di depan para pembesar istananya.
Bahkan Nabi Musa mempermalukan Fir’aun di depan pasukannya sendiri di
istana dengan mengalahkan para ahli sihirnya dengan mukjizat yang Allah
Ta’ala berikan kepadanya. Bahkan akhirnya ahli sihir Fir’aun bertobat
dan beriman kepada Allah Ta’ala. Semua ini terekam di dalam Al Quran,
surat Thaha ayat 43-76.
Para Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
Metode ini pun juga ada pada masa sahabat. Ketika Umar bin Al Khathab Radhiallahu ‘Anhu
menyampaikan khutbah di atas mimbar, dia menyampaikan bahwa Umar hendak
membatasi Mahar sebanyak 400 Dirham, sebab nilai itulah yang dilakukan
oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, jika ada yang
lebih dari itu maka selebihnya dimasukkan ke dalam kas negara. Hal ini
diprotes langsung oleh seorang wanita, di depan manusia saat itu, dengan
perkataannya: “Wahai Amirul mu’minin, engkau melarang mahar buat wanita
melebihi 400 Dirham?” Umar menjawab: “Benar.” Wanita itu berkata:
“Apakah kau tidak mendengar firman Allah:
“
.... sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya
barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?.” (QS. An
Nisa (4): 20)
Umar menjawab; “Ya Allah ampunilah, semua manusia lebih tahu dibanding Umar.” Maka umar pun meralat keputusannya. (Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 2/244. Imam Ibnu katsir mengatakan: sanadnya jayyid qawi (baik lagi kuat). Sementara Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini menyatakan hasan li ghairih)
Inilah
Umar bin Al Khathab. Beliau menerima kritikan terbuka wanita tersebut,
dengan jiwa besar dia mengakui kesalahannya, serta tidak mengatakan:
“Engkau benar, tapi caramu menasihatiku salah, seharusnya engkau
nasihatiku secara diam-diam, tidak terang-terangan!” Tidak. Umar tidak
sama sekali mengingkari cara wanita itu menasihatinya di depan banyak
manusia. Bukan hanya itu, para sahabat yang melihatnya pun tidak pula
mengingkari wanita tersebut. Jikalau wanita itu salah dalam
penyampaiannya, maka tentunya serentak dia akan diingkari oleh banyak
manusia saat itu. Faktanya tidak ada pengingkaran itu. Ini disebabkan
karena keputusan khalifah Umar, akan membawa dampak bagi rakyatnya, maka
meralatnya pun dilakukan secara terbuka.
Metode
ini juga dijalankan oleh para tabi’in serta generasi selanjutnya. Hal
ini terekam dalam kitab-kitab para ulama. Jika, mereka menasihati
pemimpin secara empat mata dan sembunyi-sembunyi, tentunya dari mana
manusia bisa tahu peristiwa-peristiwa ini? Jika ada manusia meriwayatkan
Imam Fulan telah menashati khalifah, atau gubernur, maka ini sudah
tidak bisa disebut diam-diam atau empat mata, sebab ada orang lain yang
mendengarkan atau melihat, lalu orang tersebut meriwayatkan ke generasi
selanjutnya hingga ke tangan kita.
Syaikhan
(Bukhari-Muslim) meriwayatkan tentang perilaku gubernur Madinah di
mushalla (lapangan tempat shalat Id), Marwan bin Hakam, yang telah
merubah tata cara salat Id. Beliau ingin mendahulukan khutbah dahulu,
lalu shalat Id. Beliau naik mimbar sebelum shalat, lalu Katsir bin Shalt
menegurnya: “Ghayyartum Wallahi!” (Demi Allah kau telah merubah
agama!). Nah, kisah ini amat jelas merupakan nasihat tegas kepada
pemimpin di depan umum yakni jamaah shalat Id saat itu. Dan, tak ada
yang mengatakan hal itu ‘keliru’ apalagi khawarij kepada Katsir bin
Shalt. Ya, ini sangat jelas!
Katsir bin Shalt tidak menegur Marwan dengan mendatanginya ke istana, lalu menasihatinya diam-diam. Tidak demikian.
Berikut ini adalah beberapa contoh para Imam kaum muslimin.
Sa’id bin Jubeir Radhiallahu ‘Anhu terhadap Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi
Tentang kecaman keras Said bin Jubeir Radhiallahu ‘Anhu terhadap gubernur zalim di Madinah, sangat terkenal. Beliau berkata tentang Hajjaj bin Yusuf dan pasukannya, sebagai berikut:
عن
أبي اليقظان قال: كان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون:
قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله
وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين. فلما انهزم أهل دير الجماجم لحق سعيد
بن جبير بمكة فأخذه خالد بن عبد الله فحمله إلى الحجاج مع إسماعيل بن أوسط
البجلي
“Dari Abu Al Yaqzhan, dia berkata: Said bin Jubeir pernah berkata ketika hari Dir Al Jamajim,
saat itu dia sedang berperang (melawan pasukan Hajjaj): “Perangilah
mereka karena kezaliman mereka dalam menjalankan pemerintahan, keluarnya
mereka dari agama, kesombongan mereka terhadap hamba-hamba Allah,
mereka mematikan shalat dan merendahkan kaum muslimin.” Ketika penduduk Dir Al Jamajim
kalah, Said bin Jubeir melarikan diri ke Mekkah. Kemudian dia dijemput
oleh Khalid bin Abdullah, lalu dbawanya kepada Hajjaj bersama Ismail bin
Awsath Al Bajali.” (Imam Muhammad bin Sa’ad, Thabaqat Al Kubra, 6/265. Dar Al Mashadir, Beirut)
Demikianlah salah satu kecaman keras terhadap pemimpin Madinah, oleh
seorang ulama fiqih dan tafsir, salah satu murid terbaik Abdullah bin
Abbas Radhiallahu ‘Anhuma, yakni Al Imam Sa’id bin Jubeir Rahiallahu ‘Anhu. Dia adalah imamnya para imam pada zamannya, dan manusia paling ‘alim
saat itu. Dia tidak mengatakan: “Aku akan pergi ke Hajjaj dan akan
menasihatinya empat mata!” Tidak, dan tak satu pun ulama saat itu dan
setelahnya, menjulukinya khawarij.
Imam Amr Asy Sya’bi Radhiallahu ‘Anhu terhadap Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi
Beliau
sezaman dengan Sa’id bin Jubeir, dan juga berhadapan dengan Hajjaj bin
Yusuf Ats Tsaqafi, hanya saja dia tidak sampai melakukan perlawanan
fisik.
Imam Adz Dzahabi juga menceritakan, bahwa Imam Amr Asy Sya’bi telah
mengkritik penguasa zalim, Hajjaj bin Yusuf dan membeberkan aibnya di
depan banyak manusia. Dari Mujalid, bahwa Asy Sya’bi berkata:
فأتاني
قراء أهل الكوفة، فقالوا: يا أبا عمرو، إنك زعيم القراء، فلم يزالوا حتى
خرجت معهم، فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء، فبلغني أنه قال:
ألا تعجبون من هذا الخبيث ! أما لئن أمكنني الله منه، لاجعلن الدنيا عليه
أضيق من مسك جمل
“Maka, para Qurra’ dari Kufah datang menemuiku. Mereka berkata: “Wahai Abu Amr, Anda adalah pemimpin para Qurra’.” Mereka senantiasa merayuku hingga aku keluar bersama mereka. Saat itu, aku berdiri di antara dua barisan (yang bertikai). Aku menyebutkan Al Hajaj dan aib-aib yang telah dilakukannya.”
Maka sampai kepadaku (Mujalid), bahwa dia berkata: “Tidakkah kalian
heran dengan keburukan ini?! Ada pun aku, kalaulah Allah mengizinkan
mengalahkan mereka, niscaya dunia ini akan aku lipat lebih kecil dari
kulit Unta membungkusnya.” (Ibid, 4/304)
Demikianlah Imam Amr Asy Sya’bi. Beliau mengkritik Al Hajjaj secara
terang-terangan, di antara dua pasukan yang bertikai. Dia tidak
mengatakan: “Aku akan temui Al hajjaj secara empat mata, lalu aku akan
beberkan aib-aibnya dan menasihati dia secara sembunyi.” Tidak demikian.
Imam Muhammad bin Sirin Radhiallahu ‘Anhu terhadap Ibnu Hubairah
Beliau
dikenal sebagai orang yang paling tegas terhadap Ahli bid’ah dan
penguasa yang zalim. Dia pun secara terang-terangan menegur penguasa
zamannya –yakni Ibnu Hubairah- di depan orang lain. Sebenarnya, Ibnu
hubairah adalah salah satu pejabat tinggi dalam pemerintahan Khalifah
Marwan.
Berikut ini yang diceritakan Imam Abu Nu’aim Al Ashbahani:
جعفر
بن مرزوق، قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي، قال: فدخلوا
عليه، فقال لابن سيرين: يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا، قال: رأيت
ظلماً فاشياً، قال: فغمزه ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه ابن سيرين، فقال:
إنك لست تسأل إنما أنا أسأل، فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف وإلى ابن سيرين
بثلاثة آلاف، وإلى الشعبي بألفين؛ فأما ابن سيرين فلم يأخذها.
Ja’far bin Marzuq berkata, “Ibnu Hubairah pernah memanggil Ibnu Sirin,
Al Hasan (Al Bashri), dan Asy Sya’bi, dia berkata: “Masuklah kalian.”
Maka dia bertanya kepada Ibnu Sirin: “Wahai Abu Bakar, apa yang kau
lihat sejak kau mendekat pintu istanaku?” Ibnu Sirin menjawab: “Aku
melihat kezaliman yang merata.” Perawi berkata: Maka saudaranya
menganggukan tengkuknya, dan Ibnu Sirin pun menoleh kepadanya. Lalu dia
berkata (kepada Ibnu Hubairah): “Bukan kamu yang seharusnya bertanya,
tetapi akulah yang seharusnya bertanya.” Maka, Ibnu Hubairah akhirnya
memberikan Al Hasan empat ribu dirham, Ibnu Sirin tiga ribu dirham, dan
Asy Sya’bi dua ribu. Ada pun Ibnu Sirin dia tidak mengambil hadiah itu.” (Hilyatul Auliya’, 1/330. Mauqi’ Al Warraq)
Imam Adz Dzahabi mengatakan:
قال هشام: ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين
“Berkata Hisyam: Aku belum pernah melihat orang yang paling tegas terhadap penguasa dibanding Ibnu Sirin.” (Siyar A’lam An Nubala, 4/615)
Inilah Imam Muhammad bin Sirin Radhiallahu ‘Anhu,
dia menegur kezaliman yang ada dalam istana, di depan banyak orang dan
ulama. Mereka seperti Al Hasan dan Asy Sya’bi, pun tidak
mengingkarinya. Ibnu Sirin tidak mengatakan kepada Ibnu Hubairah: “Aku
ingin katakan kepadamu secara rahasia, bahwa kezaliman di istanamu telah
merata!” Tidak demikian.
Lagi pula, tahu dari mana Hisyam, kalau Ibnu Sirin adalah manusia
paling tegas terhadap penguasa jika dia menegurnya secara
sembunyi-sembunyi?
Sufyan Ats Tsauri Radhiallahu ‘Anhu terhadap Khalifah Al Mahdi
Siapa
yang tidak kenal dengan nama ini? Imam Ahlus Sunnah, muara para ulama
pada zamannya. Di depan para sahabatnya, dia pun pernah secara
terang-terangan menegur dan menasihati Khalifah Al Mahdi yang sedang
bersama pengawalnya, bahkan membuatnya marah. Berikut ini ceritanya,
sebagaimana diceritakan oleh Imam Abu Nu’aim Al Ashbahani.
Dari ‘Ubaid bin Junad, katanya:
عطاء بن مسلم، قال:
لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه، فقال:
يا أبا عبد الله هذا خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، فأخذ
الخاتم بيده، وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين. قال عبيد: قلت لعطاء:
يا أبا مخلد قال له: يا أمير المؤمنين. قال: نعم، قال: أتكلم علي أني آمن.
قال: نعم، قال: لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني شيئاً حتى أسألك، قال:
فغضب من ذلك وهم به فقال له كاتبه: أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال:
بلى، فلما خرج حف به أصحابه، فقالوا: ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمرك أن
تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ قال: فاستصغر عقولهم ثم خرج هارباً إلى
البصرة.
’Atha bin Muslim berkata: “Ketika masa kekhalifahan Al Mahdi, dia
berkunjung ke rumah Sufyan. Ketika dia masuk, dia melepaskan dan
melemparkan cincinnya kepada Sufyan. Lalu dia berkata: “Wahai Abu
Abdillah, inilah cincinku maka berbuatlah terhadap umat ini dengan Al
Quran dan As Sunnah.” Maka Sufyan mengambil cincin itu dengan tangannya,
lalu berkata: “Izinkan aku berbicara wahai amirul mu’minin.” Berkata
‘Ubaid: Aku berkata kepada ‘Atha bin Muslim: “Hai Abu Makhlad, dia
(Sufyan) berkata kepada Al Mahdi: “Wahai Amirul mu’minin?” ‘Atha
menjawab: “Ya.”
Sufyan berkata: “Apakah aku akan aman jika aku bicara?” Al Mahdi menjawab: :Ya.” Sufyan berkata: “Jangan kau kunjungi aku hingga akulah yang mendatangimu, dan janganlah memberiku apa-apa sampai aku yang memintanya kepadamu.”
‘Atha berkata: “Maka marahlah Al Mahdi karena itu, dan dia berangan
ingin memukulnya karenanya. Maka, berkatalah sekretarisnya kepadanya:
“Bukankah kau sudah mengatakan bahwa dia aman wahai Amirul Mu’minin?” Al
Mahdi menjawab: “Tentu.” Maka, ketika dia keluar, maka para sahabat
Sufyan mengelilinginya dan bertanya: “Apa yang dia larang kepadamu
wahai Abu Abdillah, apakah dia memerintahkanmu untuk memperlakukan umat
ini dengan Al Quran dan As Sunnah?” Sufyan menjawab: “Remehkanlah akal mereka.” Lalu Sufyan Ats Tsauri melarikan diri ke Bashrah.” (Hilyatul Auliya’, 3/166. Mauqi’ Al Warraq)
Demikianlah
Imam Sufyan Ats Tsauri, memberikan teguran yang mendalam, bahkan
meminta agar para sahabatnya meremehkan akal/kecerdasan Al Mahdi dan
pengikutnya. Dia tidak mengatakan: “Biarkanlah dia, aku akan
menasihatinya secara empa mata.” Tidak. Dia langsung menegurnya, walau
di depan orang yang bersangkutan dan para pengawalnya. Inilah Imam Ahlus
Sunnah.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah
Selain
seorang ulama yang agung, beliau juga seorang mujahid. Tidak seperti
prasangka sebagian kecil manusia, yang menuduhnya tidak pernah ikut
berperang bersama kaum muslimin. Justru beliau adalah bintangnya dan
pemimpin mereka.
Beliau
juga sangat tegas dengan penyimpangan penguasa walau pun penguasa itu
muslim. Hal itu dia buktikan dengan nasihatnya yang berani dan secara
terbukan kepada Sultan Ibnu Ghazan. Syaikh Ahmad Farid menceritakan:
“Tatkala Sultan Ibnu Ghazan berkuasa di Damaskus, Raja Al Karaj datang
kepadanya dengan membawa harta yang banyak agar Ibnu Ghazan memberikan
kesempatakan kepadanya untk menyerang kaum musimin Damaskus.”
(Demikianlah rencana jahat Sultan, ingin bekerja sama dengan raja musuh
untuk menyerang kaum muslimin). Lalu Syaikh Ahmad Farid melanjutkan:
“Namun berita ini sampai ke telinga Syaikh Ibnu Taimiyah. Sehingga ia
langsung bertindak menyulut api semangat kaum muslimin untuk menentang
rencana tersebut dan menjanjikan kepada mereka suatu kemenangan,
keamanan, kekayaan, dan rasa takut yang hilang. Lalu bangkitlah para pemuda, orang-orang tua dan para pembesar mereka menuju sultan Ghazan.”
(Inilah
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ia bersama umat Islam lainnya menuju
istana Sultan untuk menentang kebijakan dan rencana jahatnya bersama
Raja Al Karaj untuk menyerang kaum muslimin Damaskus. Inilah yang orang
sekarang bilang demonstrasi. Imam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan: “Aku
akan nasihati Sultan Ghazan secara empat mata.” Justru ia melakukannya
bersama umat Islam secara terang-terangan. Apa yang akan dikatakan dan
dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, jika saat ini dia melihat ada sebuah
negara muslim yang meminta pertolongan Amerika Serikat untuk menyerang
kaum muslimin Iraq? Atau Presiden yang bermesraan dengan Zionist Yahudi
dan menutup jalur bantuan menuju Gaza, atau mengizinkan tentara kafir
membuka pangkalan militer di negeri muslim agar mereka mudah
mengendalikan negeri-negeri muslim? Dahulu ada Sultan Ibnu Ghazan dan
Raja Al Karaj yang bermesraan, namun masih ada Imam Ibnu Taimiyah. Saat
ini, ada pemimpin negeri muslim bermesraan dengan pemimpin kolonialisme
modern, AS, namun, saat ini tidak ada yang seperti Imam Ibnu taimiyah!)
Selanjutnya Syaikh Ahmad Farid mengatakan:
“Tatkala
Sultan Ghazan melihat Syaikh Ibnu Taimiyah, Allah menjadikan hati
Sultan Ghazan mengalami ketakutan yang hebat terhadapnya sehingga ia
meminta Syaikh Ibnu Taimiyah agar mendekat dan duduk bersamanya.
Kesempatan
tersebut digunakan Syaikh Ibnu Taimiyah untuk menolak rencananya, yaitu
memberikan kesempatan keada Raja Al Karaj yang hina untuk menghabisi
umat Islam Damaskus. Ibnu Taimiyah memberitahu Sultan Ibnu Ghazan
tentang kehormatan darah muslimin, mengingatkan dan memberi nasihat
kepadanya. Maka Ibnu Ghazan menurut nasihat Ibnu Tamiyah tersebut. Dari
situ, terselamatkanlah darah-darah umat Islam, terjaga isteri-isteri
mereka, dan terjaga budak-budak perempuan mereka.” (Selengkapnya lihat 60 Biografi Ulama Salaf, Hal. 797-798)
Imam Izzuddin bin Abdissalam Rahimahullah
Beliau dijuluki Shulthanul ‘Ulama
(pemimpinnya para ulama) pada masanya. Dialah ulama yang sangat
pemberani terhadap kesewenangan penguasa. Ia menegur pemimpin yang
menyimpang langsung di depannya dan dihadapan banyak manusia, bahkan
juga di mimbar khutbah Jumat.
Kami akan kutipkan sebuah peristiwa heroik beliau berikut ini:
Syaikh Al Baji (murid Imam Izzudn bin Abdisalam) mengatakan: “Syaikh
kami, Izzuddin pergi kepada Sultan Najmuddin Ayyub pada hari ‘Id di
Qal’ah (benteng Shalahuddin).
Di sana ia menyaksikan para prajurit yang berbaris di depan Sultan
Najmuddin dan dewan kerajaan saat itu. Suasana kerajaan saat itu sangat
megah. Sultan Najmuddin keluar kepada mereka dengan memakai perhiasan
sebagaimana adat para Sultan di Mesir. Para pejabat saat itu pun sujud
mencium tanah di depan sang Sultan.
Melihat peristiwa tersebut Syaikh Izzuddin menoleh kepada Sultan
Najmuddin dan berteriak memanggilnya, Wahai Ayyub! Apa hujjahmu di
hadapan Allah ketika Dia berkata kepadamu,”Aku telah berikan kerajaan
Mesir kepadamu lalu kamu memperbolehkan khamr!” Sultan Najmuddin Ayyub
berkata, “Apakah ini terjadi?” Syaikh Izzuddin menjawab, “Ya, di toko
seorang perempuan telah dijual minuman khamr dan hal-hal lain yang
munkar, sementara kamu bergelimang dalam kenikmatan kerajaan ini.”
Syaikh Izzuddin memanggilnya (sultan) dengan suara sangat keras,
sementara itu para prajuritnya membisu dan keheranan. Lalu Sultan
Najmuddin Ayyub berkata, :Wahai Tuanku, itu bukan perbuatanku, ini sudah
ada sejak zaman ayahku.” Syaikh Izzuddin berkata: “Kamu termasuk
golongan orang yang mengatakan:
"Sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak Kami menganut suatu agama,..” (QS. Az Zukhruf (43): 22)
Lalu Sultan Ayyub merencanakan meusnahkan toko tersebut.” (Ibid, 747-748)
Inilah
Imam Al ‘Izz bin Abdissalam, dengan suara lantang dia mengkritik sultan
di depan banyak manusia, dan hal itu efektif sebagai presure (tekanan) agar sultan mau menerima nasihatnya.
Bahkan,
lebih berani lagi Imam Izzuddin bin Abdissalam menganggap bahwa para
sultan saat itu masih terjerat hukum perbudakan sehingga para sultan
adalah milik baitul mal kaum muslimin. Para sultan ini boleh dijual
untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hingga wakil sultan marah dan berkata:
“Bagaimana Syaikh ini memanggil kami dan ingin menjual kami? Sementara
kami adalah raja-raja dunia. Demi Allah, aku akan penggal kepalanya!”
Namun
yang terjadi ketika wakil sultan datang ke rumah Imam Izzuddin bin
Abdissalam, justru pedangnya terjatuh, badannya gemetar karena
kewibawaan Imam Izzuudin. Wakil sultan berkata: “Wahai Tuanku, apa yang
kau inginkan?” Syaikh Izzuddin menjawab: “Aku memanggil dan menjual
kalian.” Wakil sultan bertanya: “Untuk apa kau menjual kami?” Syaikh
Izzuddin menjawab: “Demi kemaslahatan umat Islam.” Wakil sultan bertanya
lagi: “Siapa yang menerimanya?” Syaikh Izzuddin menjawab: “Akulah yang
menerimanya.” Lalu para pejabat pemerintah dipanggil satu persatu dan
dijual dengan harga mahal. Hasil penjualan mereka digunakan untuk
kemaslahatan umat Islam. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi
sebelumnya.” (Ibid, Hal. 749-750)
Ada
peristiwa yang mirip dengan masa Imam Ibnu Tamiyah. Ibnu As Subki
menceritakan tentang penguasa Damaskus bernama Shalih Ismail,
panggilannya Abu Al Khaisy. Dia berkolaborasi dengan pasukan Eropa untuk
menyerahkan kota Shida dan beneng Asy Syaqif kepada Eropa. Tindaka ini
dikecam oleh Syaikh Izzuddin sehingga dia tidak mendoakannya dalam
khutbah. Beliau tidak sendiri dalam hal ini. Beliau ditemani oleh Abu
Amr bin Al Hajib Al Maliki. Pengecaman tersebut telah membaut sultan
marah. (Ibid, Hal. 750)
Inilah
Al Imam Al ‘Izz bin Abdissalam, salah satu Imam Ahlus Sunnah bermadzhab
syafi’i. Imam Ad Dzahabi menyebutnya sebagai seorang yang sudah taraf
mujtahid, dan Imam As Suyuhi juga menyebukan di akhir hayatnya dia tidak
lagi terika madzhab, sudah berfatwa dengan fatwanya sendiri.
Demikianlah.
Sebenarnya masih banyak contoh lain dari para ulama. Namun, nampaknya
ini sudah cukup menggambarkan bahwa menasihati penguasa secara terbuka,
bukanlah hal yang tercela dan bukan pula barang baru. Justru ini adalah
perbuatan mulia yang membutuhkan keberanian sebagaimana Imam Ibnu
Taimiyah dan Imam Izzuddin bin Abdissalam.
Menasihati
pemimpin, baik secara sembunyi atau terbuka, tidaklah kita melihat dari
sisi benar-salah. Melainkan dari sisi mana di antara keduanya yang
lebih tepat guna dan efektif dalam merubah penyimpangan penguasa. Tentu
hal ini perlu kejelian dan analisa. Bisa jadi ada penguasa yang hanya
bisa berubah dengan tekanan dari rakyatnya, ada juga yang sudah bisa
berubah walau di nasihati oleh orang terdekatnya secara rahasia. Oleh
karena itu, ketenangan dan kejelian sangat diperlukan dalam memutuskan
masalah ini.
Dan,
yang jelas tak satu pun para ulama Islam mengatakan, bahwa menasihati
pemimpin secara terbuka adalah bentuk pemberontakan bahkan khawarij. Ini
adalah pengertian yang amat jauh. Tidak pantas menyamakan pemberontakan
dengan nasihat. Sebab yang satu berdosa, dan yang lain berpahala dan
mulia. Tak pantas pla hal itu disamakan dengan keluarnya kaum khawarij
terhadap pemerintahan Ali. Sebab, yang kita bahas adalah tentang
penguasa atau pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang adil seperti Ali
bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu.
Demikianlah
sikap pertama, menasihati penguasa zalim, baik dengan diam-diam, atau
terang-terangan. Kedua cara ini tergantung kesalahan yang dibuat oleh
penguasa tersebut, dan tingkat efektifitasnya. Wallahu A’lam
Sikap Kedua. Tidak Mentaatinya
Tidak mentaati penguasa yang telah keluar dari tuntunan syara’,
baik perilakunya, keputusannya, dan undang-undangnya, telah dikemukakan
Al Qur’an dan As Sunnah yang suci. Al Qur’an dan As Sunnah tidak pernah
memberikan ketaatan mutlak kepada makhluk. Ketaatan mutlak hanya kepada
Allah dan RasulNya. Ini telah menjadi kesepakatan ulama sejak dahulu
hingga kini, dan tak ada perselisihan di antara mereka.
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
“Hai
orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada RasulNya,
dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan
Rasul (As Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir …” (QS. An Nisa: 59)
Syaikh Abdurrahman bin Nashir As
Sa’di dalam tafsirnya berkata, “Perintah taat kepada Ulil Amri terdiri
dari para penguasa, pemimpin, dan ahli fatwa.” Ia mengatakan ini
bukanlah perkara yang mutlak, “tetapi dengan syarat bahwa ia tidak
memerintahkan maksiat kepada Allah. Sebab jika mereka diperintah berbuat demikian, maka tidak ada ketaatan seorang makhluk dalam kemaksiatan terhadap Khaliq. Mungkin inilah rahasia peniadaan fiil amr (kata kerja perintah) untuk mentaati mereka (athi’u),
yang tidak disebutkan sebagaimana layaknya ketaatan pada Rasul. Karena
Rasul hanya memerintah ketaatan kepada Allah, dan barangsiapa yang
mentaatinya, ia telah taat kepada Allah. Sedangkan Ulil Amri, maka
perintah mentaati mereka terikat syarat, yaitu sebatas tidak melanggar
atau bukan maksiat.” (Tafsirul Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalam Al Manan, 1/183. Cet. 1. 2000M-1420H. Muasasah Ar Risalah)
Imam Ibnu Katsir berkata, tentang makna Ulil Amri, “Ahli fiqh dan Ahli Agama, demikian juga pendapat Mujahid, ‘Atha, Hasan Al Bashri, dan Abul ‘Aliyah.” Ibnu Katisr juga mengatakan Ulil Amri bisa bermakna umara.
Lalu ia berkata: (Taatlah kepada Allah) maksudnya ikuti kitabnya,
(taatlah kepada Rasul) maksudnya ambillah sunahnya, (dan ulil amri di
antara kalian) yaitu dalam hal yang engkau diperintah dengannya
berupa ketaatan kepada Allah dan bukan maksiat kepada Allah, karena
tidak ada ketaatan kepada makluk dalam maksiat kepada Allah.
Sebagaimana dalam hadits shahih “Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal
yang ma’ruf” (HR. Bukhari). dan imam Ahmad meriwayatkan dari Imran bin
Hushain bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah.” (Tafsir Al Qur’anul Azhim, 2/345. Cet. 2. 1999M-1420H. Dar Ath Thayyibah Lin Nasyr wat Tauzi’)
Imam Nashiruddin Abul Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad, biasa dikenal Imam Al Baidhawi, berkata dalam tafsirnya, ketika mengomentari surat An Nisa’, ayat 59 (Athi’ullaha wa athi’ur rasul wa ulil amri minkum), bahwa yang dimaksud dengan ‘pemimpin’ di sini adalah para pemimpin kaum muslimin sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
dan sesudahnya, seperti para khalifah, hakim, panglima perang, di mana
manusia diperintah untuk mentaati mereka setelah diperintah untuk
berbuat adil, wajib mentaati mereka selama mereka di atas kebenaran (maa daamuu ‘alal haqqi). (Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta’wil, 1/466)
Imam Ar Razi mengatakan, taat kepada Allah, Rasul, dan Ahli ijma’ adalah pasti (qath’i), ada pun terhadap pemimpin dan penguasa, tidaklah taat secara pasti, bahkan kebanyakan adalah haram, karena mereka tidaklah memerintah melainkan dengan kezaliman (li annahum Laa ya’muruuna illa bizh zhulmi). (Mafatihul Ghaib, 5/250)
Masih banyak ayat lain yang memerintahkan tidak mentaati manusia (penguasa) yang zalim. Di antaranya firman Allah Ta’ala:
“Dan
janganlah kamu taati orang-orang yang melampuai batas.(yaitu) mereka
yang membuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.” (QS. Asy Syu’ara: 151-152)
Berkata Abul A’la Al Maududi dalam Al Hukumah Al Islamiyah,
“Janganlah engkau semua mentaati perintah para pemimpin dan panglima
yang kepemimpinannya akan membawa kerusakan terhadap tatanan kehidupan
kalian.”
Ayat lain:
“Dan
janganlah kalian taati orang yang Kami lupakan hatinya untuk mengingat
Kami dan ia mengikuti hawa nafsu dan perintahnya yang sangat
berlebihan.” (QS. Al Kahfi: 28)
Taat kepada penguasa yang zalim merupakan bentuk ta’awun (tolong menolong) dalam dosa dan kesalahan, padahal Allah Ta’ala berfirman: “Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan kesalahan.” (QS. Al Maidah:2)
Dalam hadits juga tidak sedikit tentang larangan mentaati perintah kemaksiatan, di antaranya:
Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda: “Dengar dan taat atas seorang muslim dalam hal yang ia sukai
dan ia benci, selama ia tidak diperintah untuk maksiat. Jika diperintah
untuk maksiat, maka jangan dengar dan jangan taat.” (HR. Bukhari. Al Lu’lu’ wal Marjan, no. 1205)
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya taat itu hanya dalam hal yang ma’ruf” (HR. Bukhari dari Ali radhiallahu ‘anhu. Al lu’lu’ wal Marjan, no. 1206)
Abu bakar Ash Shidiq Radhiallahu ‘Anhu
berkata pasca pengangkatannya menjadi khalifah, “Taatlah kalian
kepadaku selama aku taat kepada Allah dan RasulNya, apabila aku
melanggar Allah dan RasulNya, maka jangan taat kepadaku.” Ibnu Katsir mengatakan sanadnya shahih. (Al Bidayah wa An Nihayah, 5/269. Cet. 1. 1988M-1408H. Dar Ihya Ats Turats)
Khalifah Umar Al Faruq radhiallahu ‘anhu juga berkata dalam salah satu khutbahnya, “Sesungguhnya tidak ada hak untuk ditaati bagi orang yang melanggar perintah Allah.”
Ringkasnya, Al Qur’an, As Sunnah, atsar sahabat, mufasirin dan fuqaha, semua sepakat bahwa taat kepada pemimpin hanya jika ia di atas kebenaran, jika dalam pelanggaran maka tidak boleh ditaati.
Sikap Ketiga: Mencopot Pemimpin Zalim dari Jabatannya
Pemimpin merupakan representasi dari umat, merekalah yang mengangkatnya melalui wakilnya (Ahlul Halli wal Aqdi), maka mereka juga berhak mencopotnya jika ada alasan yang masyru’ dan logis.
Bapak sosiolog Islam, Ibnu Khaldun juga mengatakan
tidak boleh dikatakan ‘memberontak’ bagi orang yang melakukan
perlawanan terhadap pemimpin yang fasiq. Beliau memberikan contoh
perlawanan Al Husein terhadap Yazid, yang oleh Ibnu Khaldun disebut
sebagai pemimpin yang fasiq. Apa yang dilakukan oleh Al Husein adalah
benar, ijtihadnya benar, dan kematiannya adalah syahid. Tidak boleh dia
disebut bughat (memberontak/makar) sebab istilah memberontak hanya ada jika melawan pemimpin yang adil. (Muqaddimah, Hal. 113)
Ketahuilah, yang dilawan oleh kaum khawarij adalah pemimpin yang sah dan adil, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu.
Sedangkan yang kita bincangkan adalah perlawanan terhadap penguasa yang
zalim dan tiran, sebagaimana yang banyak dilakukan aktifis gerakan
Islam di banyak negara saat ini. Tentu nilai perlawanan ini tidak sama.
Ternyata
pandangan ini dibenarkan oleh banyak ulama (sebenarnya para ulama
berselisih pendapat tentang pencopotan penguasa yang zalim).
Imam At Taftazani dalam Syarah al Aqaid an Nafsiyah meriwayatkan bahwa Imam Asy Syafi’i radhiallahu ‘anhu berpendapat bahwa Imam bisa dicopot karena kefasikan dan pelanggarannya, begitu juga setiap hakim dan pemimpin lainnya.
Imam Abdul Qahir Al
Baghdadi mengatakan, “Jika pemimpin menjauhkan diri dari penyimpangan,
maka kepemimpinannya dipilih karena keadilannya, sehingga kesalahannya
tertutup oleh kebenaran. Jika ia menyimpang dari jalan yang benar, maka
harus dilakukan pergantian, mengadilinya, dan mengambil kekuasaannya.
Dengan demikian, ia telah diluruskan oleh umat atau ditinggalkan sama
sekali.”
Imam Al
Mawardi menyatakan ada dua hal seorang Imam telah keluar dari
kepemimpinannya, yaitu ia tidak adil dan cacat fisiknya. Cacat
keadilannya bisa bermakna mengikuti hawa nafsu dan melakukan syubhat. Ketidakadilan bisa juga bersifat individu seperti meninggalkan shalat, minum khamr, atau urusan umum seperti menyalahgunakan jabatan. (Imam Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, Hal. 28).
Imam Al
Ghazali berkata, “Seorang penguasa yang zalim hendaknya dicopot dari
kekuasaannya; baik dengan cara ia mengundurkan diri atau diwajibkan
untuk dicopot. Dengan itu ia tidak dapat berkuasa.”
Imam
Al Ijli mengatakan, “Umat berhak mencopot Imam tatkala ada sebab yang
mengharuskannya, atau sebagaimana yangdikatakan pensyarah, sebab yang
membahayakan umat dan agama.”
Imam
Ibnu Hazm berkata, “Imam Ideal wajib kita taati, sebab ia mengarahkan
manusia dengan kitabullah dan sunah rasulNya. Jika ada menyimpang dari
keduanya, maka harus diluruskan, bahkan jika perlu diberi hukuman had . jika hal itu tidak membuatnya berubah, maka ia harus dicopot dari jabatannya dan diganti orang lain.”
Sebenarnya para ulama ini berbeda pendapat Menurut tentang alasan pencopotannya. Imam Syafi’i dan Imam Al
Haramain mensyaratkan jika penguasa itu fasik dan melanggar. Imam Asy
Syahrustani mengatakan; kebodohan, pelanggaran, kesesatan, dan
kekufuran. Imam Al Baqillani menyebutkan jika Imam telah kufur,
meninggalkan shalat wajib, fasik, mengambil harta orang lain, mengajak
ke yang haram, mempersempit hak sosial, dan membatalkan hukum-hukum
syariat. Imam Al Mawardi menyatakan; ketidak adilan dan cacat fisik.
Sementara
Ulama lain (pandangan ahli hadits) yang berpendapat agar kita bersabar
terhadap pemimpin yang zalim, ini juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah, ada juga ulama yang membenarkan keduanya, antara bersabar atau
memberikan perlawanan agar ia dicopot dari jabatannya. Wallahu A’lam wa Lillahil ‘Izzah

Farid Nu’man Hasan
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا”
[النساء : 59]
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.”
“أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ… ” (متفق عليه)
“Ketahuilah! Setiap kalian adalah penjaga dan pengurus, setiap kalian
akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dijaga dan diurusnya.
Seorang pemimpin manusia adalah penjaga dan pengurus, dia akan diminta
pertanggungjawaban atas rakyatnya…
“Wajib diketahui bahwa kepemimpinan yang mengatur urusan manusia
adalah bagian dari kewajiban-kewajiban agama, bahkan tidak mungkin agama
tegak tanpa kepemimpinan. Karena manusia tidak akan mampu mewujudkan
kepentingan bersama kecuali dengan berkumpul, karena sebagian manusia
membutuhkan sebagian yang lain, di mana wajib ada seorang pemimpin dalam
perkumpulan mereka itu… dan karena Allah I mewajibkan amr ma’ruf dan
nahy munkar, dan itu tidak akan terlaksana tanpa kekuatan dan
kepemimpinan. Begitu pula kewajiban-kewajiban lainnya, seperti jihad,
keadilan, pelaksanaan haji, jum’at, hari raya, membela orang yang
teraniaya dan pelaksanaan hukuman tidak akan terlaksana tanpa kekuatan
dan kepemimpinan. Dari itu diriwayatkan sabda Rasulullah r:” السلطان ظل
الله في الأرض”
Sultan itu adalah bayang-bayang Allah di bumi. Ada pula yang mengatakan
bahwa enam puluh tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik dari pada
satu malam tanpa pemimpin. Dan pengalaman membuktikan semua itu.
Oleh karena itu para ulama salaf seperti Fudhail bin ‘Iyadh dan Ahmad
bin Hanbal dan yang lainnya berkata: “Seandainya kami punya doa yang
dikabulkan, maka pasti kami menjadikan doa itu untuk pemimpin.”
Maka wajib menjadikan kepemimpinan sebagai agama dan sarana untuk
mendekatakan diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah
dengan ketaatan kepada pemimpin dalam ketaatan kepada-Nya dan kepada
Rasul-Nya merupakan ibadah yang paling utama. Dan sesungguhnya kerusakan
yang terjadi pada kebanyakan manusia adalah karena keinginan merebut
kekuasaan dan mendapatkan harta darinya. (Majmû’ Fatâwâ,
XXVIII/390-391).
“السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ
وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ” (متفق عليه)
“Patuh dan taat (kepada pemimpin) adalah kewajiban orang Muslim, baik
dalam hal-hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak
perintah untuk maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat, maka tidak ada
kepatuhan dan ketaaatan.”
“مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى
اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ
الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ
وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ
فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ
مِنْهُ” (متفق عليه)
“Barang siapa taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah dan siapa
membangkang kepadaku berarti membangkang kepada Allah. Barang siapa taat
kepada pemimpin berarti ia taat kepadaku, dan siapa membangkang kepada
pemimpin, berarti ia membangkang kepadaku. Sesungguhnya pemimpin itu
laksana perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya
pelindung. Maka apabila dia memerintah untuk takwa kepada Allah dan
berlaku adil, ia akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak demikian,
maka dia berdosa karenanya.
“Di antara hak-hak para pemimpin atas rakyatnya adalah kepatuhan dan
ketaatan dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan
meninggalkan apa yang mereka larang, selama tidak bertentangan dengan
syari’at Allah, tapi apabila bertentangan dengan syari’at Allah, maka
tidak boleh patuh dan taat, “Tidak boleh taat kepada makhluk dalam
maksiat kepada Khaliq (Allah).
Sesungguhnya merupakan bagian dari ketaatan kepada pemimpin yang
Allah perintahkan, yaitu seorang mu’min menjalankan peraturan-peraturan
yang ditetapkan pemerintah bila tidak bertentangan dengan syari’at.
Selama ia menjalankan peraturan itu berarti ia taat kepada Allah dan
Rasul-Nya, ia akan mendapat pahala atas perbuatan itu. Dan barangsiapa
menentangnya berarti ia membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia
berdosa karenanya.
Adapun hak-hak rakyat atas pemimpin mereka adalah tanggung jawab
besar dan urusan yang sangat penting. Sebenarnya bukanlah maksud dari
kepemimpinan itu untuk melebarkan kekuasaan dan mendapat kedudukan, tapi
untuk mengemban tanggung jawab yang besar yang terpusat pada penegakkan
hak di antara manusia dengan meninggikan agama Allah dan menciptakan
kemaslahatan bagi umat manusia baik dalam urusan agama maupun dunia.
(Dinukil dari Risalah huqûq al-Râ’î wa al-Ra’iyyah, karya Syaikh
Utsaimin, oleh Muhammad Nashir al-‘Uraini dalam Wujûb Thâ’at al-Sulthân,
hal. 25).
« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ
وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
». (متفق عليه)
“Agama itu adalah nasihat”, kami (para sahabat) bertanya: “Untuk
siapa?” untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan
umat muslim seluruhnya.”
“ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا
إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَلُزُومُ
الْجَمَاعَةِ “(رواه أحمد )
“Tiga sifat yang tidak menjadikan iri hati seorang muslim selamanya,
ikhlas beramal untuk Allah, menasihat para pemimpin dan setia kepada
jama’ah.”
“مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ
عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ
مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ” (رواه
أحمد)
“Barang siapa ingin menasihati sultan dalam suatu urusan, maka
janganlah menampakkannya secara terang-terangan, tetapi hendaklah ia
mengambil tangannya lalu berdua dengannya. Jika ia menerima nasihatnya,
maka itu sebuah kebaikan. Jika tidak, maka telah melaksanakan
kewajibannya.”
“Adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, mereka adalah
pemimpin tertinggi, pemimpin daerah, hakim, dan semua yang mempunyai
kekuasaan baik besar maupun kecil, tugas dan kewajiban mereka lebih
besar dari yang lainnya, mereka wajib mendapat nasihat sesuai dengan
tingkatan dan kedudukan mereka, yaitu dengan meyakini kepemimpinan
mereka, mengakui kekuasaan mereka, taat kepada mereka dengan
,
tidak memberontak dan mengajak rakyat untuk mentaati mereka dan
melaksanakan perintah mereka yang tidak bertentangan dengan perintah
Allah dan Rasul-Nya, serta mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki
untuk menasihati mereka dan menjelaskan apa yang tidak jelas bagi mereka
dalam hal-hal yang mereka butuhkan untuk kepemimpinan mereka sesuai
dengan kondisi masing-masing, berdoa untuk kebaikan mereka dan agar
mendapat taufik, karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat.
Tidak boleh mencela dan menghina mereka dan menyebarkan aib mereka,
karena pada yang demikian terdapat keburukan dan kerusakan yang besar.
Karena salah satu bentuk nasihat untuk mereka adalah berhati-hati dan
memperingatkan orang lain dari perbuatan itu. Dan siapa yang melihat
dari mereka tindakan yang tidak benar maka ia harus memperingatkan
mereka dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, dengan lemah
lembut dan menggunakan ungkapan yang tepat agar tercapai maksud yang
dituju. Cara memberi nasihat seperti itu tepat untuk setiap orang,
apalagi bagi para pemimpin, pasti mendapatkan banyak kebaikan, juga
sebagai pertanda kejujuran dan keikhlasan.
Dan saya memperingatkan kepada orang yang member nasihat dengan cara
yang terpuji seperti ini, agar tidak merusak nasihatnya dengan ingin
mendapat pujian manusia, seperti dengan mengatakan: “Sungguh aku telah
menasihati mereka dan mengatakan kepada mereka begini dan begitu.” Yang
demikian itu adalah tanda riya dan lemahnya keikhlasan dan terkandung
banyak madarat.” (Al-Riyâdh al-Nâdhirah, hal. 49-50)
“وَمَنْ لَهُ وَالٍ فَيَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله
فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الله وَلاَ يَنْزَعُ يَدًا مِنْ
طَاعَتِهِ” (رواه ابن حبان)
“Barang siapa mempunyai pemimpin, lalu ia melihatnya melakukan
maksiat kepada Allah, maka hendaklah ia membenci kemaksiatannya, akan
tetapi jangan melepaskan ketaatan.”
“Kami berpendapat tidak boleh memberontak kepada pemimpin-pemimpin
kita walaupun mereka berbuat zalim, juga tidak boleh mendoakan keburukan
untuk mereka, tidak melepaskan ketaatan kepada mereka. Dan kita
memandang bahwa taat kepada mereka adalah bagian dari taat kepada Allah,
selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat. Dan kita selalu berdoa
untuk kebaikan dan keselamatan mereka.” (Syarh al-‘Aqidah
al-Thahawiyyah, hal. 368)
“Ketahuilah bahwa kezaliman penguasa tidak mengurangi kewajiban yang
diwajibkan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Dia akan menanggung akibat
kezalimannya sedangkan kebaktian dan kebaikan kamu yang dilakukan
bersamanya tetap sempurna insyaallah, seperti shalat jama’ah, shalat
jum’at, jihad bersama mereka dan segala bentuk ketaatan laksanakanlah
bersama mereka. Apabila kamu melihat seseorang mendoakan keburukan untuk
mereka, ketahuilah orang tersebut adalah pengikut hawa nafsu, dan
apabila kamu melihat seseorang berdoa untuk kebaikan mereka, ketahuilah
bahwa dia adalah pengikut sunnah.” (Thabaqât al-Hanâbilah, Abu Ya’la,
II/36)
“لاَ تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ وَلاَ تَغِشُّوهُمْ وَلاَ تُبْغِضُوْهُمْ
وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا فَإِنَّ الأَمْرَ قَرِيبٌ ” (رواه البيهقي)
“Janganlah kalian mencela pemimpin kalian, jangan pula berbuat curang
dan membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena
sesungguhnya urusan itu dekat.”
“Sebagian orang memiliki kebiasaan membicarakan para pemimpin di mana
saja ia berada, merusak kehormatan mereka, mennyebarkan keburukan dan
kesalahan mereka, seraya berpaling dari kebaikan dan kebenaran mereka.
Tidak diragukan bahwa perbuatan seperti ini dan merusak kehormatan para
pemimpin tidaklah memperbaiki keadaan, tidak memecahkan masalah atau
menghilangkan kezaliman. Justru menambah kesulitan di atas kesulitan,
menyebabkan kebencian terhadap para pemimpin dan tidak melaksanakan
perintah mereka yang seharusnya ditaati. Dan kita tidak ragu bahwa para
pemimpin memiliki keburukan dan kesalahan seperti halnya manusia yang
lain, karena setiap manusia pasti bersalah dan sebaik-baik orang yang
bersalah adalah yang bertaubat… (Dinukil dari Risalah huqûq al-Râ’î wa
al-Ra’iyyah, karya Syaikh Utsaimin, oleh Muhammad Nashir al-‘Uraini
dalam Wujûb Thâ’at al-Sulthân, hal. 23).
[1] . H.R. Baihaqi (Syu’ab al-Îmân, VI/17), dihasankan oleh Syaikh Albani (Zhilâl al-Jannah , II/224)lla








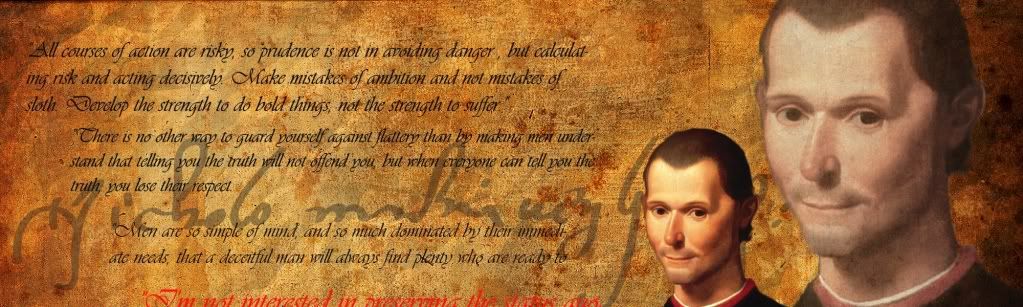














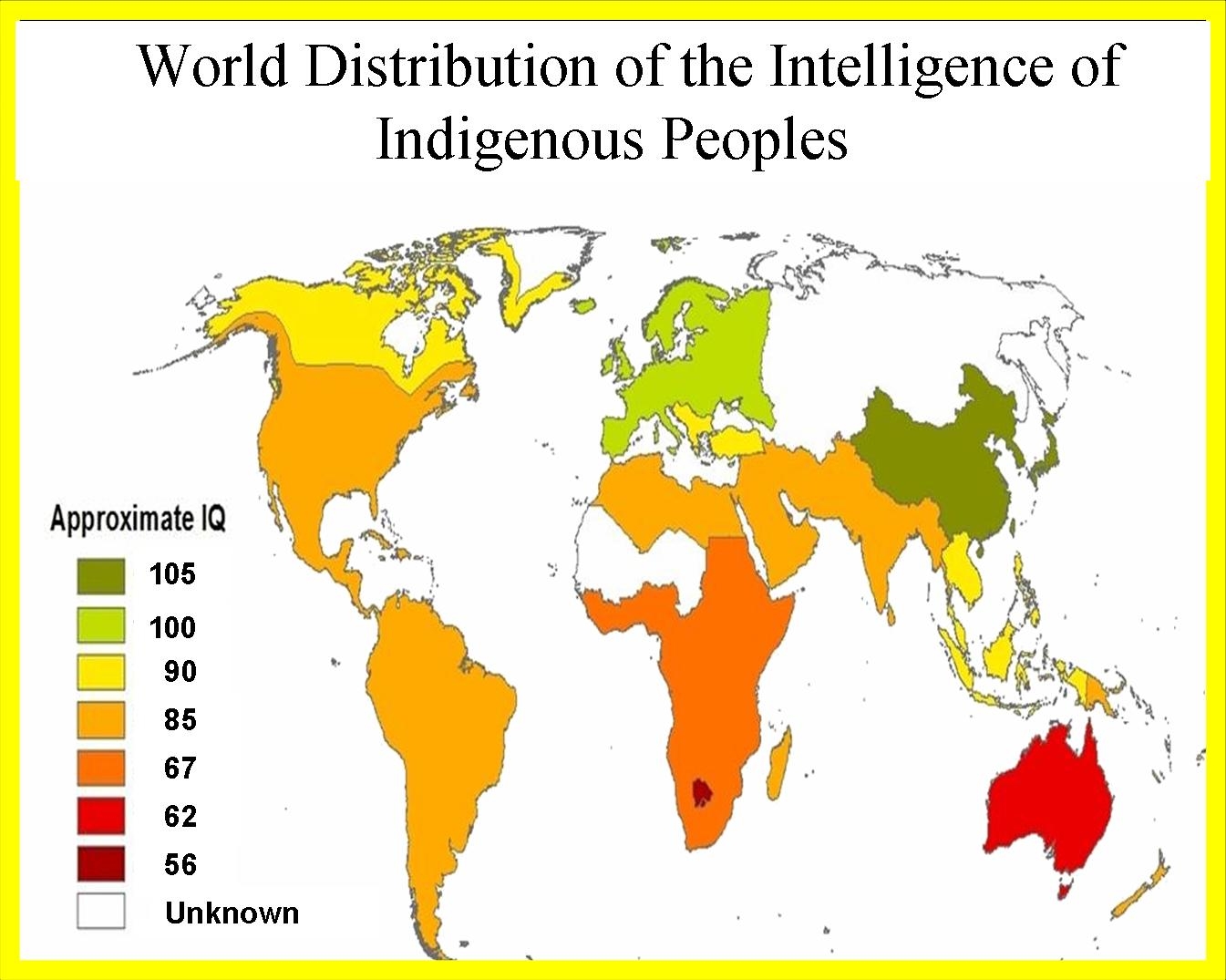




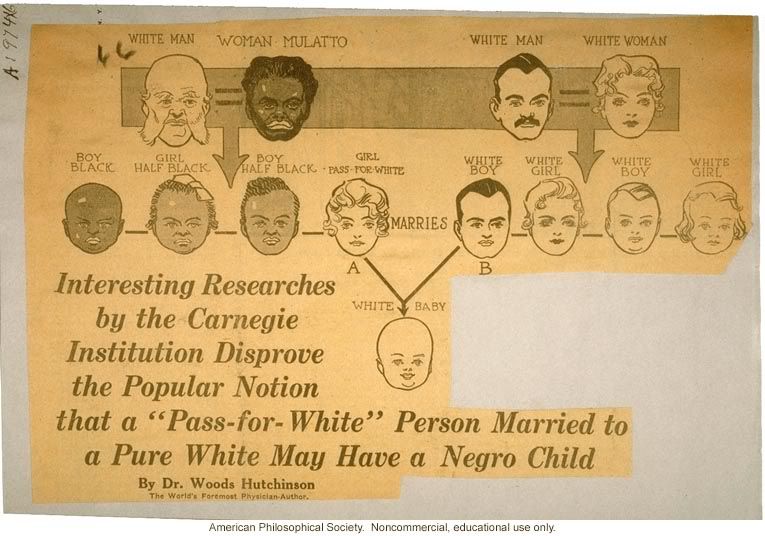
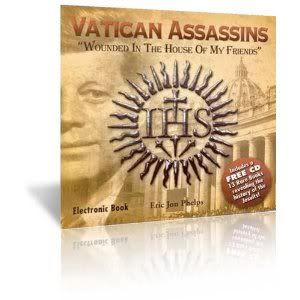









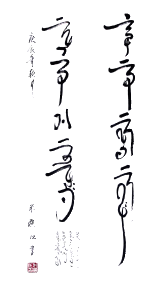
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_special.gif)





